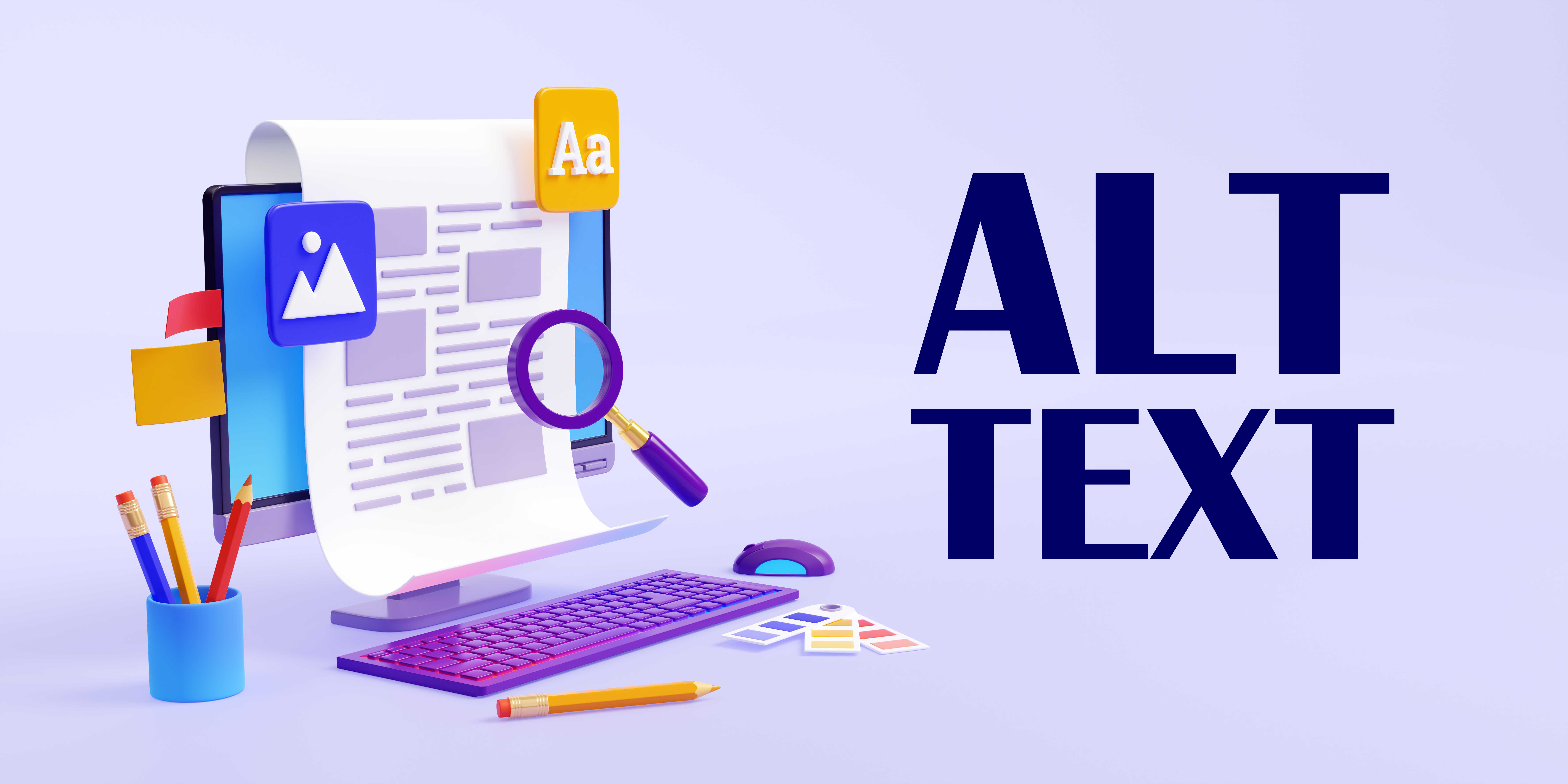Puluhan jurnalis tampak antusias mengikuti Diskusi Jurnalisme Inklusif Berbasis Disabilitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Sabtu (30/9/2023).
Dalam diskusi yang dihelat di Balai RW 12, Gg. Empu Gandring VI, RW 12, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terungkap bahwa profesi jurnalis dan media memiliki peranan penting bagi terwujudnya keadilan.
Namun tidak jarang, jurnalis dan media terjebak dalam praktik clickbait journalism, glorifikasi hingga diskriminasi. “Kami melihat, isu disabilitas kurang mendapatkan perhatian di ruang redaksi,” kata Ketua AJI Yogyakarta, Januardi Husin.
Dikatakannya, mudah ditemukan pemberitaan di media tidak sensitif. Mulai dari pemilihan diksi bermasalah yang berdampak menyinggung para disabilitas, pemilihan angle tulisan yang memuat glorifikasi, hingga melakukan praktik ekspolitasi dengan menjual kesedihan disabilitas.
“Itulah sebab mengapa isu disabilitas ini menjadi penting bagi jurnalis dan media,” ungkap Juju—panggilannya.
Kode Etik Jurnalistik (KEJ), lanjutnya, telah memuat aturan bahwa jurnalis tidak boleh melakukan praktik diskriminatif maupun eksploitasi terhadap kelompok minoritas apapun. Itu menjadi aturan umum yang harus dipegang oleh jurnalis.
“Tetapi untuk menerjemahkan aturan-aturan yang umum, dibutuhkan aturan yang lebih detail mengenai isu disabilitas. Saat ini, Dewan Pers juga telah membuat pedoman peliputan isu disabilitas. Pedoman ini perlu dipelajari, dicermati dan dipraktikkan oleh jurnalis,” katanya.
Koordinator Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI), Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), Sholih Muhdlor mengatakan, memang, sekarang ini telah banyak liputan-liputan tentang disabilitas.
“Namun dari sekian banyak berita dirasa masih belum inklusif. Baik dari sisi pemilihan kata, isu, maupun pemilihan angle. Cenderung mengandung sensasional, belas kasih dan sebagainya. Artinya, belum banyak berita yang memuat nilai memberdayakan,” katanya.
Menurutnya, tidak jarang media memberitakan disabilitas secara heroik. Misalnya, ada berita orang dengan kaki diamputasi bisa menaklukkan Gunung Everest. “Seorang Tuna Netra Juarai Ajang Tarik Suara Dunia” dan seterusnya.
“Jangankan, disabilitas, teman-teman non—disabilitas pun tidak banyak yang bisa melakukan itu. Ini sebetulnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan disabilitas. Yang terjadi justru glorifikasi. Ini kontra—produktif, semua orang akan menuntut bahwa semua disabilitas juga bisa melakukan itu. Padahal setiap orang punya kemampuan berbeda. Ini sering diabaikan,” katanya.
Berita bermuatan “heroisme” cenderung lebih ditonjolkan, sedangkan isu lain yang mengangkat martabat disabilitas cenderung sedikit tersentuh media. Misalnya, pekan olahraga disabilitas nasional maupun daerah, termasuk atlet disabilitas belum banyak pemberitaan.
“Ada pemberitaan pun masih sebatas ajang disabilitas menunjukkan kemampuan, belum sampai pada tahap pemberdayaan. Termasuk terkait kekerasan terhadap penyandang disabilitas cenderung tenggelam,” katanya.
Sejauh ini, lanjut Sholih, negara telah mulai hadir. Regulasi baik level nasional, provinsi, kabupaten maupun kota, telah mulai melibatkan disabilitas. “Namun pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas belum klir dalam memberikan pelayanan secara inklusif dengan mengedepankan martabat,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga mendengarkan penjelasan narasumber dari Dewan Pers dan jurnalis Tempo, Cheta Nilawaty Prasetyaningrum. (*)





![[Pers Rilis] Merefleksikan Kembali Gerakan Bersama Mengawal Implementasi UU TPKS](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/03/Banner.png?resize=150%2C150&ssl=1)