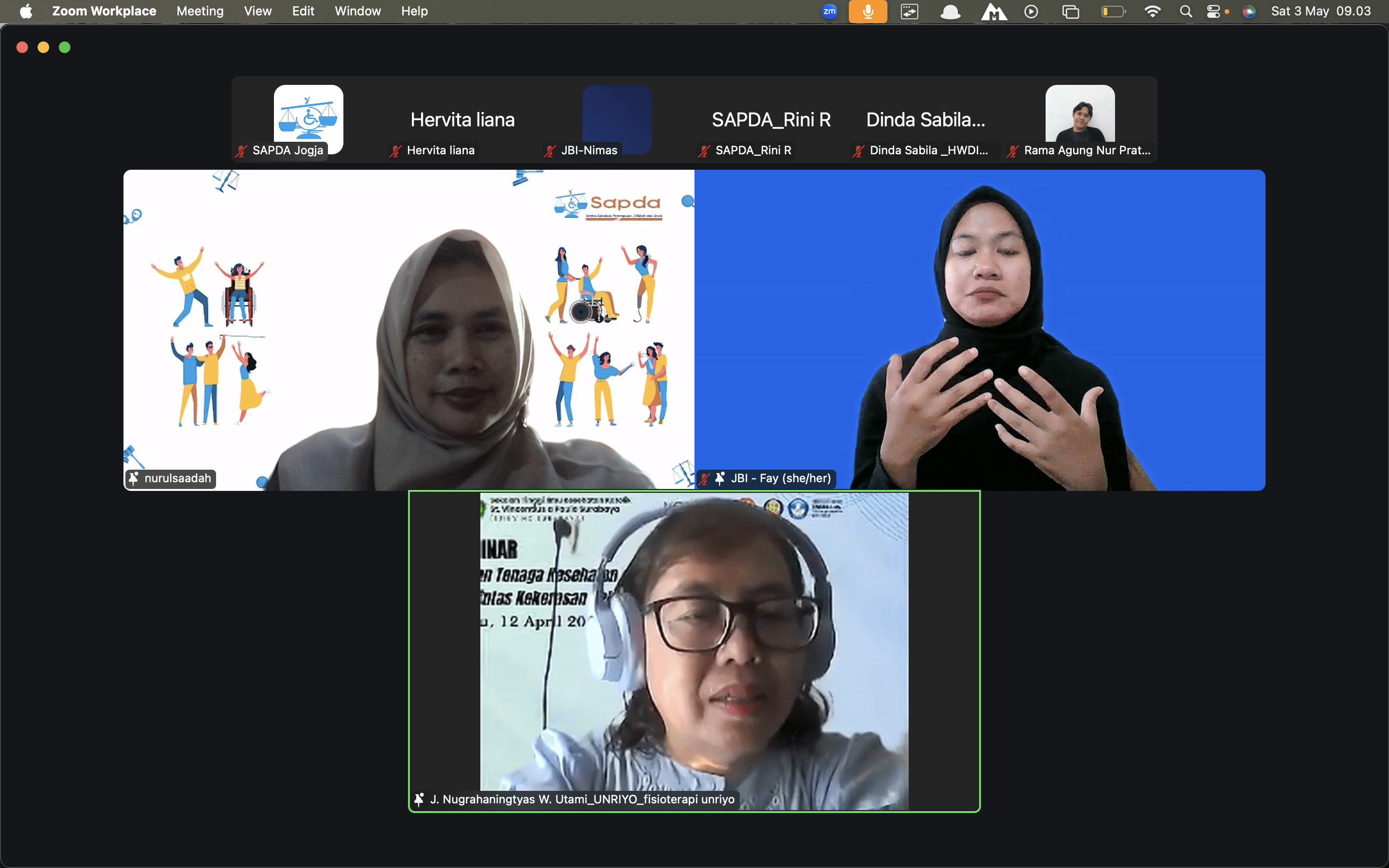Identitas Buku
Judul : Agama dan Kesehatan Reproduksi
Editor : M. Imam Aziz, Elga Sarapung, Masruchah
Penerbit : Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation
Tebal : xxii + 327 halaman
Terbit : 1991 (cetakan pertama)
Resensi buku oleh: Robi Kurniawan (Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Agama di Meja Keadilan Jender
Agama sedang ditantang, dan penantangnya adalah Feminisme. Feminisme bukan sekadar ideologi kesetaraan, namun juga sebuah pengingat: bahwa kemapanan dan status quo tak selamanya bisa bertahan dan dipertahankan.
Demikian semangat yang kita temukan dalam buku Agama dan Kesehatan Reproduksi yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, bekerja sama dengan Yayasan kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation ini. Meski buku tersebut telah diterbitkan pertama kali jauh pada tahun 1999, dan salah seorang penulisnya telah wafat seperti Almarhum Gusdur, buku ini terus bergema sampai hari ini.
Gusdur dan beberapa penulis lainnya, terdiri dari kalangan agamawan, akademisi, aktivis dan pekerja sosial rembukan dalam sebuah seminar yang diadakan waktu itu, Seminar Nasional ‘Perempuan, Agama, Kesehatan Reproduksi, dan Etika Global’. Semangat mereka sama, yaitu membicarakan ulang beberapa isu tentang perempuan yang terus menerima ketidakadilan atas dirinya, baik di ranah keluarga, politik dan publik. Dan lebih spesifik lagi, isu besar yang menjadi sabab ketidakadilan tersebut adalah agama.
Uniknya, dalam makalah dan ceramah seminar yang dikumpulkan dalam buku ini, posisi agama sebagai isu besar yang berkaitan erat dengan ketidakadilan atas perempuan tidak untuk ditinggalkan, tidak untuk dilemahkan, dan tidak untuk semata-mata dicela sebagai penyebab utama ketidakadilan atas perempuan. Melainkan agama sebagai bagian yang mesti dikritisi, dibaca ulang, diinterpretasi ulang, dan bukannya tidak mungkin; untuk dirangkul sebagai landasan-landasan yang dapat dipakai pejuang kesetaraan gender untuk memperoleh haknya. Ya, karena pada dasarnya, semua penulis dalam buku ini, sepakat bahwa agama hadir untuk meninggikan harkat martabat manusia, menyerukan pada kesetaraan dan keadilan.
Keadilan Gender
Gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab manusia laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya. Di pembicaraan lain, Gayle Rubin (1975) mendefinisikan gender sebagai konstruksi dan tatanan sosial mengenai perbedaan-perbedaan di antara jenis kelamin yang mengacu pada relasi-relasi sosial di antara perempuan dan laki-laki. Dalam dua definisi ini, kita menemukan dua kata kunci yang patut dibicarakan lebih lanjut perihal gender; Pembagian peran laki-laki dan perempuan dan konstruk sosial yang menciptakan relasi pembagian atau pemisahan peran tersebut.
Sientje Merentek-Abram, Ketua Badan Pengurus Pusat Persekutuan Wanita berpendidikan Teologi di Indonesia (PERAWATI) dalam bab ‘Kesetaraan Gender dalam Agama’ mengatakan, peran secara gender dibedakan dari peran kodrati yaitu peran yang dilaksanakan berdasarkan kodrat. Peran gender yang telah ditetapkan secara budaya, terbuka untuk dipertukarkan antara pria dan wanita. Sementara peran kodrati, seperti mengalami haid, melahirkan serta menyusui pada wanita dan kemampuan menghasilkan sperma pada pria, adalah peran yang tidak dapat dipertukarkan karena sudah demikian sejak diciptakan (lihat halaman 36).
Gender perlu dibedakan dengan seks. Istilah seks mengacu pada struktur reproduksi dan sering dikaitkan dengan alat untuk mencapai kepuasan secara biologis. Singkatnya seks mengandung makna biologis, dan istilah gender mengacu pada makna sosial, budaya dan juga psikologis. Sebab itu, berbicara perihal gender tentu dimulai dengan pembacaan, seiring dengan kata kunci di atas, konstruk sosial seperti apa yang menciptakan pembagian peran yang telah seperti itu? Budaya –yang juga berarti wacana dan pengetahuan- apa yang melanggengkan konstruk sosial itu? Dan bagaimana masing-masing subjek sosial memandang dirinya (psikologis) dalam pembagian peran yang telah ada?
Jika dapat disimpulkan, sebagaimana yang diceritakan dalam buku ini, konstruk sosial telah menciptakan perempuan dalam dominasi laki-laki. Dalam berbagai aspek, misalnya dalam pembagian peran dalam keluarga, laki-laki diidentikkan sebagai makhluk yang kuat, mampu bersaing, dan berpikir rasional, sehingga pantas disematkan sebagai orang yang berhak dan bertanggung jawab mencari pekerjaan di luar rumah, memutuskan permasalahan dan arah rumah tangga. Sedangkan perempuan diidentikkan sebagai pihak yang lemah, terbatas, dan lembut, sehingga peran yang pantas untuknya adalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mendidik anak dan patuh pada suami. Pembagian peran seperti ini bahkan telah kita ketahui dari materi pelajaran sekolah, semisal; Ibu memasak, Ayah pergi ke sawah; Ani bermain boneka, dan Budi bermain mobil.
Dewasa ini pembagian peran tersebut tidaklah dapat diamini saja sebagai perkara yang tidak bermasalah. Pembagian peran tersebut nyatalah telah menghambat masing-masing pihak, bukan perempuan saja. Laki-laki akibat sekat peran tersebut, seperti kurang mendapatkan hangatnya rumah tangga bersama anak-anak karena lebih banyak keluar rumah ataupun dianggap ‘tak elok’ jika bekerja di ranah-ranah yang ‘dimapankan sebagai milik perempuan’ seperti bekerja di salon, di dapur atau mengasuh anak. Bagi perempuan juga demikian. Perempuan kesulitan masuk ke ranah publik, tak dianggap cakap mengambil keputusan politik, dan bahkan tak layak memimpin.
Konstruk sosial yang demikian terus berlanjut ke arah yang lebih parah; Dominasi laki-laki atas perempuan, penerjemahan perempuan oleh laki-laki. Ketika satu pihak dianggap lebih tinggi dan lebih layak dibandingkan pihak lain, di sini nampaklah ketidakadilan tersebut. Dan ketidakadilan mesti hilangkan. Dan untuk menghilangkannya tentulah dengan mencari akar kondisi yang menyebabkan ketidakadilan tersebut. Jika akar yang menopang struktur sosial tersebut adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat seperti Agama, apa salahnya jika nilai tersebut dikritisi? Dan mari membawa agama ke “Meja Pengadilannya”.
Agama dan Kritik Gender
Agama untuk manusia, ataukah manusia untuk agama? Ungkapan ini muncul dalam bagian dialog –yang juga menjadi keunikan- dalam buku ini. Pertanyaan tersebut diungkapkan J.B. Banawiratma, dosen Teologi di Yogyakarta, sebagai jawaban atas pertanyaan, Apakah agama tidak akan kehilangan makna moral apabila reinterpretasi itu (atas teks-teks agama) tidak dibatasi? Banawiratma menjawab, baginya Agama untuk manusia. Agama tidaklah kehilangan apa-apa dengan kerja-kerja manusia. Jadi, suatu praktik agama tidak lagi memperkembangkan hidup kemanusiaan, maka agama ini harus dipertanyakan; benarkah agama seperti itu. Ini bisa disalahtafsirkan tetapi saya kira yang saya maksudkan jelas. Agama untuk manusia. Maksudnya adalah apabila umat beragama tidak memperjuangkan hal-hal yang manusiawi, maka akan dipertanyakan tanggung jawab agamanya (lihat halaman 90).
Mempertanyakan bagaimana agama membahas gender adalah salah satu upaya kita menilai agama dalam ketidakadilan gender. Dan reinterpretasi adalah salah satu upaya tersebut. Reinterpretasi atas teks-teks keagamaan penting karena teks tersebut adalah dasar moral aktivitas keseharian manusia (intertekstualitas). Reinterpretasi diperlukan karena pada dasarnya agama tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi Gereja Khatolik dijelaskan:
“Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asal mula yang sama (….)… memang karena berbagai kemampuan fisik maupun kemacam-ragaman daya kekuatan intelektual dan moral tidak dapat semua orang disamakan”.
Tetapi setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan, karena bertentangan dengan maksud Allah. Sebab sungguh layak disesalkan, bahwa hak-hak asasi pribadi itu belum dimana-mana dipertahankan secara utuh dan aman. Seperti bila seseorang perempuan tidak diakui wewenangnya untuk dengan bebas memilih suaminya dan menempuh status hidupnya, atau untuk menempuh pendidikan dan meraih kebudayaan yang sama seperti dipandang wajar bagi laki-laki. Kecuali itu, sungguhpun antara orang-orang terdapat perbedaan-perbedaan yang wajar, tetapi kesamaan martabat pribadi menuntut agar dicapailah kondisi hidup yang lebih manusiawi dan adil” (Konsili Vatikan II, Gaudium et spes 29).
Namun masalahnya timbul pada pelaksanaan dan juga penafsiran Alkitab berkenaan dengan ayat yang berbeda-beda atau nampaknya bertentangan. Misal dalam (1) Kitab Kejadian 1:1-2:4a, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah (Imago Dei), dan (2) kitab Kejadian 2:4b-25: Penciptaan manusia laki-laki dan perempuan dari debu tanah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Laki-laki diciptakan pada tahap pertama, perempuan diciptakan setelah laki-laki. Disini kita melihat pertentangan. Pada ayat (1) kita menyaksikan kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai ciptaan Allah. Dan di ayat (2) kita melihat keutamaan laki-laki daripada perempuan, dengan didahulukannya laki-laki. Sientje mengatakan, sampai sejauh ini, tidak ada masalah dengan kedua narasi tersebut (ayat 1 dan 2). Problem muncul, ketika dalam perjalanan sejarah gereja, narasi kedualah yang populer dipakai sebagai alat untuk menentukan tempat yang “layak” bagi perempuan. Sedangkan narasi pertama yang mempunyai potensi untuk menghadirkan pemahaman mengenai kesetaraan, jarang dikemukakan, seolah-olah tidak ada ayat lain, selain narasi kedua yang perlu dikembangkan.
Seiring dengannya, Budhy Munawar juga mempersoalkan ketegangan Hermeneutis dalam penafsiran teks-teks Islam. Budhy memaparkan teks-teks Islam telah direpresentasikan dengan berbagai model penafsiran, seperti tafsir tradisional, tafsir feminis, penafsiran feminis reformis, penafsiran feminis transformis, penafsiran feminis rasionalis dan penggunaan hermeneutika postmodern dalam feminisme. Berbagai model penafsiran tersebut tentu menghasilkan pembacaan yang berbeda. Namun, harapnya, berbagai penafsiran tersebut dapat membawa umat beragama pada sesuatu yang lebih tinggi: Tidak hanya pencarian transformasi kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, emosional, intelektual dan spiritual bagi perempuan saja, tetapi juga pencarian makna terdalam dari arti penciptaan laki-laki dan perempuan. Pencarian pada esensi Tuhan.
Banawiratma bahkan lebih jauh meminta umat beragama, khususnya Khatolik. Ia menawarkan kita mengambil kesempatan untuk bertaubat atas diskriminasi jender yang telah dan terus terjadi selama ini. Dan seterusnya dapat melakukan berbagai upaya, misalnya:
1. Mengakui dosa sexism, dominasi, subordinasi, dan diskriminasi
2. Menghilangkan penindasan dan subordinasi terhadap perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan, lembaga-lembaga serta paguyuban-paguyuban kita.
3. Memikirkan kembali pandangan-pandangan iman kita (teologi) terutama mengenai Yesus Kristus dan mengenai gereja.
4. Mengembangkan program-program pastoral untuk mengurangi atau menghapus penderitaan korban diskriminasi, subordinasi dan dominasi serta memajukan perkembangan kemanusiaan sepenuhnya.
Agama Ngomongin AIDS, Aborsi dan Kesehatan Reproduksi
Pembahasan diatas barangkali masih cukup abstrak untuk pembaca. Hebatnya lagi, buku ini juga ditantang membicarakan isu-isu laten yang melingkupi perempuan dan kaum ibu, seperti AIDS, Aborsi dan Reproduksi. Di satu sisi memang ketiganya adalah persoalan medis. Tapi kita mesti ingat, pembicaraan gender adalah juga tentang pembicaraan kondisi sosial, budaya dan psikologis yang melingkarinya. Ketiga problem diatas dekat dengan perempuan. Dan Sebab itu, agama sebagai institusi sosial, dalam kajian gender, juga dituntut mampu membicarakan persoalan tersebut. Karena itulah buku ini semakin relevan.
Posisi agama dalam hal ini berada diranah moril dan etis. Tata moril dan etis yang berlaku di masyarakat kita jelas telah memposisikan penderita AIDS sebagai orang yang tak bermoral, menikmati gaya seks bebas, dan tak jarang dikucilkan masyarakat. Begitu pula dengan menggugurkan kandungan, penghakiman masyarakat atas tindakan menggugurkan kandungan tak memberikan jalan keluar. Di sini agama tak boleh mendiamkan. Persoalannya bukan lagi pada apakah penyebabnya haram atau halal. Namun jauh dari itu, persoalannya hari ini adalah bagaimana agama mampu menciptakan iklim masyarakat yang mengerti dengan risiko-risiko pergaulan bebas dan aborsi. Juga pada bagaimana agama mampu membentuk umat yang mampu bersikap ‘sepantasnya’ jika di tengah mereka ditemui penderita AIDS atau perempuan yang menggugurkan kandungannya.
J. Chr. Purwawidyana, Ketua Pengadilan Gerejani (Vicarus Iudicialis) mengatakan perlunya usaha Pastoral, yang berarti usaha untuk menolong perempuan yang kandungannya menimbulkan masalah agar perempuan tersebut tidak tergoda menggugurkan kandungan. Ada beberapa kegiatan yang dapat diusahakan:
1. Perlunya pendidikan seksualitas dengan maksud agar orang semakin menyadari luhurnya seksualitas dan tidak bermain-main dengannya;
2. Perlunya penjelasan mengenai metode kontrasepsi yagn manusiawi dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Perlunya lembaga sosial yang dirintis oleh swasta maupun pemerintah untuk menolong perempuan yang berada dalam kesulitan, jika berdasarkan etikat baik, dia mau mempertahankan kandungannya;
4. Perlunya pengembangan usaha menciptakan suasana hidup masyarakat yang dapat memahami dan menerima perempuan yang terlanjur hamil tanpa suami resmi. Hal itu tidak baik, tetapi tidak ada gunanya terus menghukum perempuan yang mendapatkan kecelakaan seperti itu.
Begitu juga dengan persoalan AIDS, Eka Darmaputera Ketua Umum Persekutuan Gereja (PGI) Pusat mengatakan, agama-agama semestinya mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa walaupun yang harus diperangi adalah virus, namun terkait dengan masalah HIV/AIDS adalah penyakit-penyakit sosial yang cukup serius. Bila penyakit-penyakit ini tidak berhasil kita atasi secara mendasar, maka upaya-upaya pencegahan apapun terhadap perluasan penularan HIV/AIDS tidak akan efektif (lihat halaman 219).
Dan masih banyak lagi banyak lagi pandangan-pandangan agamawan yang mesti disimak dalam buku ini seperti; Chuzaimah Tahido Yanggo, Ketua Pusat Studi Wanita IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang membicarakan aborsi dalam sudut pandang Islam; dan Gedong Bagus Oka dalam bab Beberapa Catatan tentang Aborsi dari Sudut Agama Hindu.
Dengan membaca buku ini, diharapkan pembaca dapat mengerti apa saja tantangan perempuan dan agama dalam perjuangan kesetaraan (equality) gender, menghapus diskriminasi gender dan keluar dari dominasi patriarkhi. Sebagai penutup, baik juga rasanya saya kutip omongan Gusdur yang juga diambil dari buku ini:
“Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh para penganut formalisme agama adalah ketidakmampuannya melakukan reinterpretasi atas ajaran-ajaran agama yang sudah tertanam begitu lama… (….) Kuncinya sebenarnya terletak pada sejauh mana kesediaan para pemimpin agama formal untuk mempertaruhkan status quo yang selama ini mereka nikmati sebagai sasaran tembak dari proses reinterpretasi ajaran agama.[]
*




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)