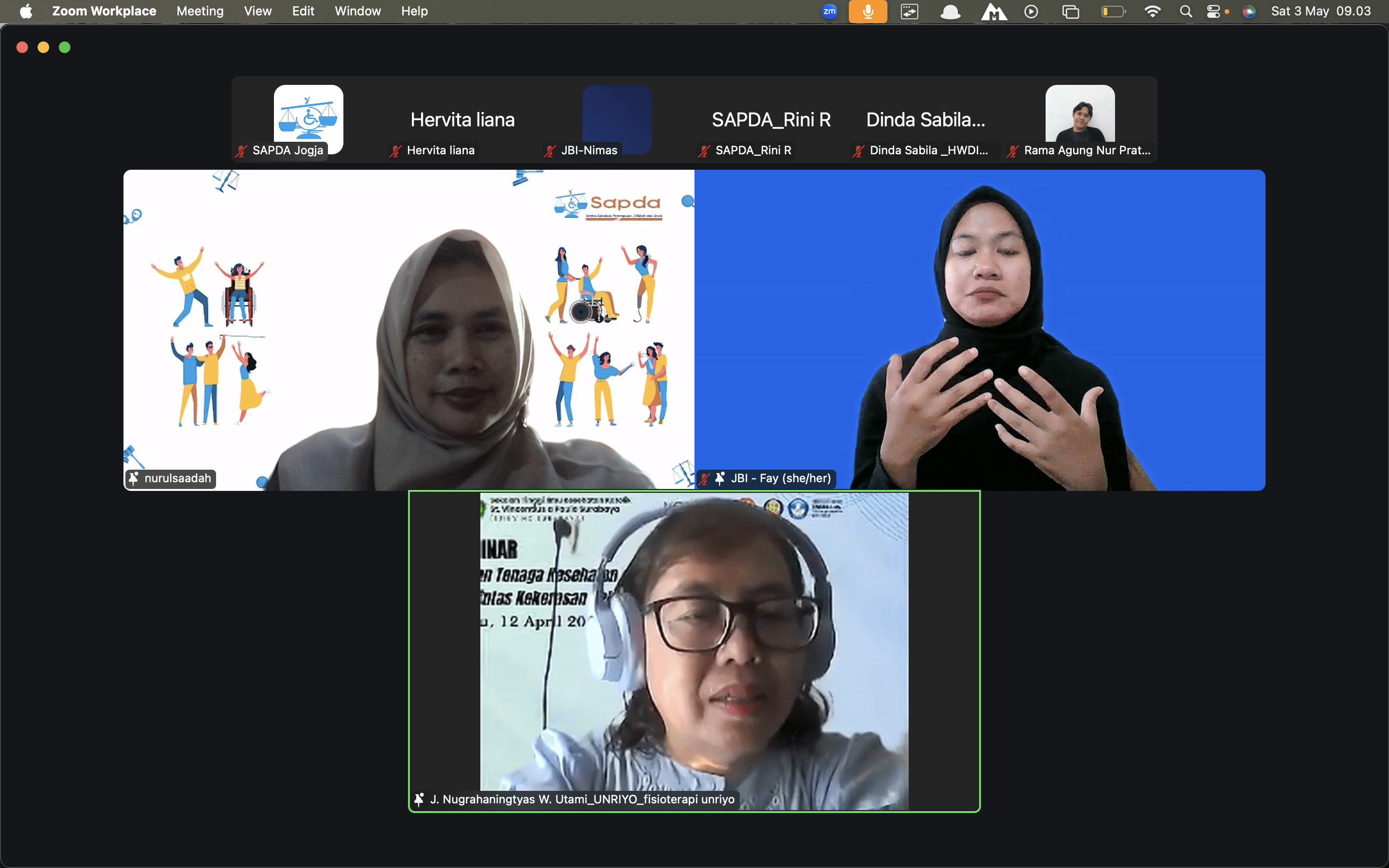Meliput isu disabilitas memiliki tantangan tersendiri. Jurnalis perlu memperhatikan rambu-rambu tertentu ketika mewawancarai, mengambil gambar, menulis, maupun melakukan aktivitas jurnalisme lainnya yang melibatkan penyandang disabilitas, sehingga pemberitaan yang dihasilkan tidak jatuh ke dalam stereotip dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas.
Cheta Nilawaty, jurnalis dari kanal Tempo Difabel menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meliput isu disabilitas. Ketika mewawancarai penyandang disabilitas misalnya, jurnalis perlu memperhatikan hambatan dan kebutuhan khusus sesuai dengan ragam disabilitasnya. Cheta mencontohkan, ketika membuat janji dengan penyandang disabilitas kursi roda, jurnalis perlu memperhatikan aksesibilitas tempat.
“Enggak mungkin mau wawancarai seorang narasumber disabilitas daksa yang letaknya misalnya di restauran dengan empat anak tangga tanpa ramp. Itu enggak mungkin. Bagaimana nanti narasumber masuknya? Itu harus dipikirkan,” ujar Cheta saat menjadi narasumber dalam lokakarya Jurnalisme Inklusif Berbasis Disabilitas yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada akhir September 2023.
“Contoh lain, kita enggak mungkin kan mau mewawancarai seorang disabilitas mental psikososial itu dalam keadaan mereka sedang relap, stres atau tekanannya besar. Kita harus menunggu masa tenang dulu, baru kita bisa wawancara. Itu harus dipikirkan,” lanjutnya.
Cheta juga mengingatkan jurnalis juga perlu hati-hati dalam menulis berita seputar isu disabilitas. Ia menyayangkan masih banyak jurnalis yang masih menggunakan istilah penyandang cacat. “Itu sudah jadul sekali. Sekarang Undang-Undang yang baru nomor 8 tahun 2016 itu pentebutannya bukan lagi penyandang cacat, tetapi penyandang disabilitas. Sebagai subyek berita itu harus diperhatikan,” tegasnya.
Selain itu, ketika menyebutkan ragam disabilitas misalnya, jurnalis sebaiknya mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. “Ini masih banyak yang kebalik balik. Saya pernah membaca berita, ada yang menulis penyandang disabilitas mental sosial itu menjadi disabilitas intelektual. Itu berbeda,” kata Cheta.
Narasumber lainnya, Sholih Muhdlor dari GEDSI SAPDA juga menambahkan sejumlah tips bagi para jurnalis ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Sholih mengatakan, pada dasarnya, berbicara kepada penyandang disabilitas sama dengan berbicara dengan orang-orang pada umumnya. “Bagaimana cara bertanya kepada mereka? Tanya saja seperti biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa teman-teman ajukan kepada narasumber non disabilitas itu juga bisa diajukan kepada mereka,” kata Sholih.
Sholih menambahkan, ketika merasa ragu untuk mewawancarai penyandang disabilitas, jurnalis bisa mempertimbangkan perlibatan pendamping. Pendamping bisa jadi adalah orang tua, pasangan, keluarga atau bisa jadi orang lain yang ditugaskan untuk mendampingi dan memiliki kedekatan dengan penyandang disabilitas secara emosional.
Namun, Sholih mengingatkan, kehadiran pendamping tidak untuk menggantikan peran penyandang disabilitas. Jika narasumber adalah penyandang disabilitas Mental misalnya, kehadiran pendamping hanya berfungsi untuk menjaga kondisi emosionalnya. Demikian pula ketika narasumber adalah penyandang disabilitas Tuli, kehadiran Juru Bahasa Isyarat sekedar untuk menerjemahkan proses komunikasi.
“Kita tetap harus berinteraksi langsung dengan penyandang disabilitas sebagai subyek. Jangan kemudian kita mengarahkan pertanyaan atau informasi kepada pendamping atau Juru Bahasa Isyaratnya. Dengan begitu, kita menganggap teman disabilitas itu sebagai manusia yang memiliki martabat dan manusia yang utuh, terlepas dari apa yang ada pada mereka,” tegas Sholih.
Tips lainnya, Sholih juga mengatakan jurnalis terkadang perlu untuk memilih kalimat-kalimat yang sederhana dalam memberikan pertanyaan kepada penyandang disabilitas, termasuk mengajukannya secara satu per satu. Hal ini utamanya ketika narasumber ialah penyandang disabilitas Intelektual yang memiliki hambatan dalam menyerap informasi dan memilih diksi, atau penyandang disabilitas Tuli yang memiliki keterbatasan pembendaharaan kata.
“Jangan memakai pertanyaan beruntun. Ajukanlah pertanyaan itu dengan sederhana dan satu per atu dan tunggu mereka selesai memberikan jawaban, dan jangan terburu-buru untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya ketika mereka belum selesai bicara. Saya pikir ini adalah sebuah etika jurnalisme yang juga umum. Menunggu orang selesai bicara,” katanya.
Sementara itu, Suprapto dari Komisi Pendidikan Dewan Pers mengatakan etika meliput isu disabilitas pada dasarnya sudah menjadi bagian dari kode etik jurnalisme yang perlu dipatuhi oleh setiap jurnalis.
“Dalam pasal 8 misalnya, kita dalam menulis berita itu tidak boleh merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa dan cacat jasmani. Artinya, kita tidak boleh dalam pemberitaan itu melakukan diskriminasi baik berdasarkan suku, ras, warna kulit, jenis kelamin maupun karena keterbatasan orang lain atau teman-teman disabilitas,” jelasnya.
Ia menyayangkan, pemberitaan-pemberitaan yang muncul di media jurnalistik masih ditemukan bernada negatif, bermuatan stigma dan stereotip. Menanggapi situasi tersebut, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.
Suprapto tidak menampik bahwa peraturan ini masih perlu disosialisasikan agar dapat diterapkan secara optimal oleh setiap institusi pers yang terdaftar di Dewan Pers. Salah satu caranya, Dewan Pers akan memasukan muatan pedoman pemberitaan ramah disabilitas ke dalam uji kompetensi jurnalistik.
“Dengan begitu, kita bisa mendorong teman-teman jurnalis untuk membaca aturan dan menerapkannya ke dalam karya jurnalistik mereka. Nanti lembaga yang akan merumuskan soal-soal uji kompetensi tidak hanya terpaku pada Undang-undang pers dan kode etik jurnalistik semata, tetapi juga pedoman-pedoman lain yang sudah diterbitkan Dewan Pers, tentu termasuk di dalamnya Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas,” jelasnya.
Lokakarya jurnalisme inklusif berbasis disabilitas merupakan bagian dari langkah advokasi SAPDA dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)