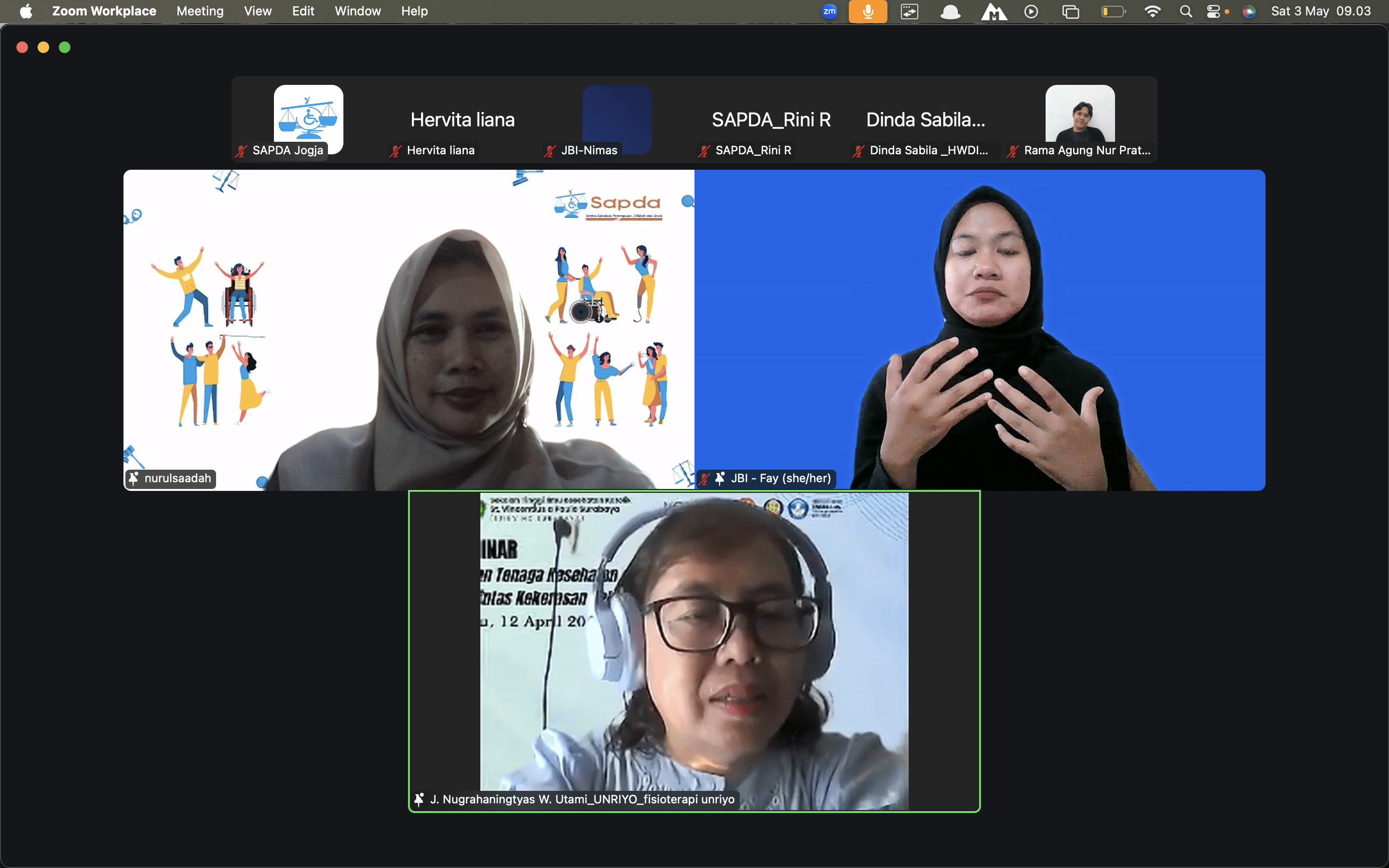Sudah lebih dari satu tahun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diterbitkan, namun implementasinya di dalam penanganan kasus masih menyisakan berbagai catatan. Situasi ini tidak terkecuali pula pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi yakni berkaitan dengan pemenuhan akomodasi yang layak. Pasal 25, 66, dan 70 UU TPKS sendiri telah memandatkan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, termasuk penilaian personal, dalam proses peradilan.
“APH, pengada layanan, penyedia layanan medis belum memahami betul apa itu aksesibilitas dan akomodasi yang layak, sebagai hak paling mendasar bagi penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara,” kata Koordinator Layanan Rumah Cakap Bermartabat, Arini Robi Izzati, dalam konferensi pers Percepatan Pengesahan Aturan Pelaksana dan Implemantasi UU TPKS yang diselenggarakan oleh Jaringan Perempuan pada Senin (27/11) dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Arini mengatakan, walaupun telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, belum semua lembaga menuangkan regulasi ini ke dalam aturan internal masing-masing. “Sampai sejauh ini hanya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung yang memiliki peraturan internal soal akomodasi yang layak, itu pun belum cukup tersosialisasi sampai tingkat pelaksana,” pungkasnya.
Situasi kemudian diperburuk dengan masih minimnya perspektif yang dimiliki aparat penegak hukum, pengada layanan dan tenaga medis tentang situasi kerentanan dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Padahal, ada atau tidak adanya perspektif akan sangat berpengaruh terhadap proses pemeriksaan.
“Misalnya, seorang penyidik yang cukup memiliki perspektif disabilitas akan lebih mudah diajak berdiskusi untuk memahami situasi korban disabilitas, duduk bersama dengan pendamping dan psikolog dalam memformulasikan pertanyaan, merumuskan model bertanya dengan disabilitas korban kekerasan seksual, dan memahami kebutuhan khusus korban selama pemeriksaan,” tutur Arini.
Selain itu, Arini juga menyayangkan hampir belum ada penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang memberikan pemberatan hukuman pidana bagi pelakunya. Padahal, Pasal 15 UU TPKS memandatkan bahwa hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual ditambahkan satu per tiga ketika korbannya adalah penyandang disabilitas.
“Hal ini patut disayangkan mengingat penerapan pasal tambahan masa hukuman pada dasarnya merupakan pengejawantahan kondisi kerentanan korban disabilitas oleh karenanya pelaku hukumannya patut untuk di perberat,” ujarnya.
Mandat UU TPKS lainnya yang juga masih menyimpan banyak catatan di dalam implementasinya adalah Pasal 30 tentang restitusi sebagai hak korban. Restitusi sendiri merupakan ganti kerugian materil dan imateril yang diberikan oleh pelaku. Arini bercerita, beberapa penyelesaian kasus kekerasan seksual pada penyandang disabilitas memang berujung pada dikabulkannya permohonan restitusi. Namun, hal ini sebenarnya hanyalah kemenangan di atas kertas karena kebanyakan pelaku dalam kondisi miskin dan tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi.
“Sedangkan sampai saat ini belum ada mekanisme yang bisa menggantikan pembayaran restitusi terhutang. Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban sampai saat ini belum ada. Selaku pendamping kadang dilemma untuk menjelaskan restitusi. Satu sisi ini hak korban, tapi pendamping tahu ini mustahil eksekusinya karena pelaku tidak mampu,” keluh Arini.
Di samping itu, Juru Bicara Jaringan Perempuan Yogyakarta sekaligus Konselor Hukum Women Crisis Center Rifka Annisa, Nurul Kurniati, mengatakan hingga saat ini belum banyak aparat penegak hukum yang menerapkan UU TPKS pada kasus kekerasan seksual. Beberapa alasan yang sering dikemukakan antara lain belum ada peraturan turunan dari UU TPKS, belum ada petunjuk teknis pelaksana yang jelas, dan masih ada kekurangan dari sisi anggaran dan infrastruktur.
Jaringan Perempuan Yogyakarta kemudian memberikan sejumlah rekomendasi untuk mendorong percepatan implementasi UU TPKS, yakni:
- Membuat forum bagi aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan UU TPKS dan menyamakan persepsi.
- Koordinasi dan diskusi bersama-sama lembaga layanan perempuan dan anak untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan UU TPKS.
- Mendorong percepatan pengesahan aturan turunan UU TPKS sebagai aturan pelaksana yang dapat di implementasi sampai tingkat daerah dan desa serta dusun dalam prinsip non diskriminasi, kesetaraan gender, inklusi dan berperspektif pada pemulihan pemenuhan hak-hak korban TPKS.
- Memastikan kebijakan, anggaran dan implementasi yang berperspektif pada pemulihan pemenuhan hak-hak korban.
Konferensi pers selengkapnya dapat disimak di sini.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)