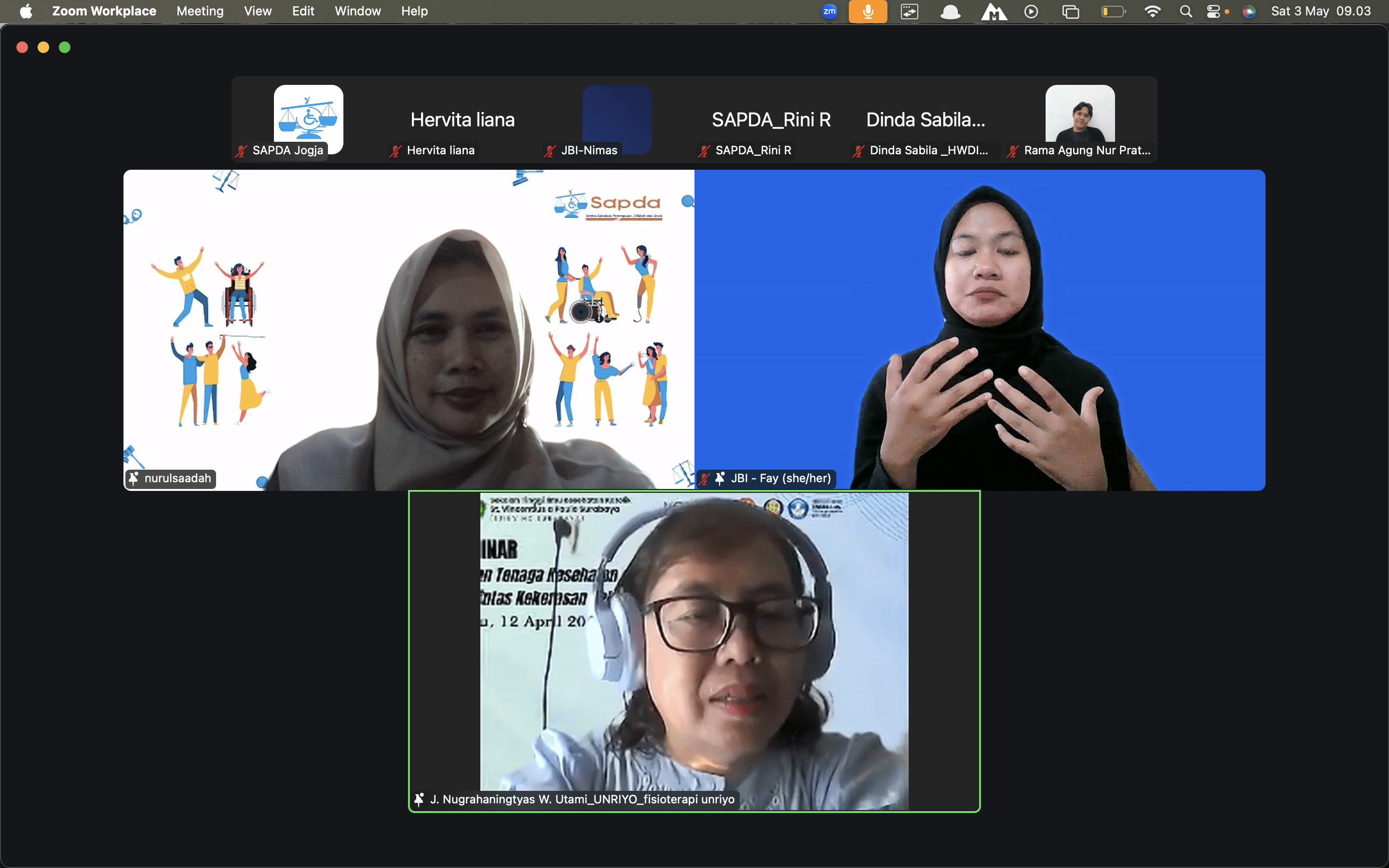Ini merupakan pengalaman yang penulis alami sendiri pada tanggal 3 Februari 2013. Selama ini penulis meyakini betul bahwa memang ada diskriminasi terhadap difabel dan orang – orang yang dianggap tidak sama dengan kebanyakan orang. Istilah tidak sama ini bisa bermakna apa saja. Tidak hanya difabel, bisa juga dimaknai dengan orang – orang yang memiliki pola pikir berbeda dengan orang lain sehingga dia dianggap menyimpang dari normalitas. Namun keyakinan penulis ini awalnya semata – semata hanya berbentuk konstruksi pemikiran hingga suatu hari penulis menyaksikan sendiri bagaimana diskriminasi tersebut.
Semua bermula saat SAPDA –salah satu NGO yang concern terhadap isu–isu disabilitas melakukan sebuah agenda yaitu evaluasi terhadap sekolah Difabel, Gender, dan Kesehatan Reproduksi yang sudah berlangsung selama 3 bulan di salah satu rumah makan yang berlokasi di sekitar Candi Prambanan. Kebetulan peserta evaluasi yang juga perserta sekolah SAPDA tidak hanya dari kalangan non difabel tapi juga ada beberapa kawan difabel. kawan difabel itu datang bersama suaminya yang juga merupakan seorang difabel. penolakan mungkin merupakan sebuah tindakan yang amat akrab terdengar ditelinganya tetapi beliau tidak akan pernah menyangka bahwa di siang itu dia akan mengalami peristiwa penolakan yang tidak akan gampang dilupakan. Langkah ringan mengiringi perjalanannya sampai ke rumah makan tersebut. namun siapa yang mengira, siang yang harusnya menjadi menyenangkan karena akan bertemu dengan rekan–rekan yang memiliki visi dan misi yang sama harus menjadi hari yang tidak akan terlupakan. Kawan dan suaminya ini dibentak oleh salah seorang oknum rumah makan tersebut. Tidak diketahui dengan pasti apa status oknum ini apakah dia pegawai rumah makan tersebut, tukang parkir ataukah petugas keamanan karena pakaiannya yang tidak menggunakan seragam sehingga tidak bisa diidentifikasikan posisi dia di rumah makan tersebut sebagai apa.
Dia mengusir dan membentak kawan difabel saya tadi. Oknum tersebut mengira kawan saya ini akan mengemis di area rumah makan. Yang kemudian menjadi miris adalah oknum tersebut melakukan pengusiran sebelum meminta penjelasan dan klarifikasi terlebih dahulu terhadap kawan saya ini. Oknum tersebut bahkan tidak mengetahui ada keperluan apa kawan saya ini. Padahal jelas–jelas kawan saya ini memakai kaos seragam sekolah SAPDA yang sama dengan yang saya kenakan. Karena di usir, maka kawan saya ini pun mulai berjalan ke arah jalan raya dan berniat pulang dengan langkah berat. Namun niat pulang kawan saya ini harus terhenti karena dia bertemu dengan rekan–rekan saya yang lain yang juga menghadiri acara evaluasi ini. Kawan saya satunya ini bertanya mengapa berjalan kearah jalan raya dan kawan saya yang difabel pun menjelaskan semua yang dia alami. Yang kemudian cukup disesalkan adalah oknum tersebut tidak memberikan pernyataan maaf ataupun tindakan lain untuk menebus kesalahan praduga yang dia lakukan tadi. Lagaknya seolah–olah dia melakukan tindakan yang luar biasa penting karena mengusir pengemis yang akan mengganggu kenyamanan makan bagi para pengunjung rumah makan ini. Sepertinya dia sudah sering melakukan tindakan ini karena tidak tampak sedikit pun penyesalan di raut mukanya.
Cerita diatas memberikan gambaran baru bagi saya bahwasanya diskriminasi terhadap kawan–kawan difabel masih sangat mudah ditemukan dimana–mana. Kasus itu pun mungkin hanya menjadi salah satu kasus yang mencuat kepermukaan dibandingkan dengan berjuta kasus di luar sana yang coba ditutupi oleh difabel yang mengalami diskriminasi itu sendiri. Sejak dahulu, permasalahan mengenai diskriminasi dan stereotype selalu menjadi permasalahan yang melekat pada diri difabel. gaung dengan dikeluarkannya Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ataupun Peraturan Daerah Provinsi DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak–Hak Penyandang Disabilitas yang selama ini kencang terdengar dimana–mana nyatanya tidak pernah menyentuh masyarakat pada akar rumput. Isu difabilitas pun seolah–olah hanya menjadi isu elitis yang ramai diperbincangkan oleh beberapa kalangan semata seperti akademisi, stakeholders ataupun orang–orang yang sedikti banyak bersinggungan dengan isu–isu disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya.
Bagaimana masyarakat mau berbicara mengenai penghargaan hak asasi manusia pada difabel jika konstruksi pemikiran mereka mengenai difabel masih sama seperti pada tahun 1900-an. Dimana difabel dimaknai sebagai pihak–pihak kelas dua. Bukan orang–orang yang juga disananya dilekati harga diri dan hak asasi yang menuntut untuk dipenuhi. Bagaimana bisa stakeholder berbicara mengenai impian mewujudkan lingkungan yang inklusif jika dibandingkan dengan penolakan–penolakan yang terus menerus terjadi dimana–mana terhadap kawan–kawan difabel. Bagaimana bisa impian yang selalu diucapkan oleh kawan–kawan difabel yang ingin hidup secara nyaman tanpa mengalami diskriminasi dapat terwujud jika saja mereka masih mengalami perlakuan–perlakuan yang tidak mengenakkan kemanapun mereka melangkah di permukaan bumi ini.
Perjuangan mewujudkan kesetaraan bagi kawan–kawan difabel pun menjadi tidak sinergis ketika para petinggi mengecam bahwa perlakuan terhadap difabel di Yogyakarta sudah sangat baik. Pemerintah menganggap dirinya sudah mengambil langkah yang dianggap revolusioner dengan mengeluarkan Perda pertama di Indonesia berkaitan dengan perlindungan hak–hak difabel. tapi masyarakat akar rumput sendiri tidak pernah mengetahui bagaimana tata cara berhadapan dengan difabel. menjadi sebuah ironi ketika kemudian kasus diskriminasi ini masih terjadi bahkan di tahun 2013 dimana pembicaraan mengenai permasalahan difabel harusnya mulai bergeser ke bagaimana peranan pemerintah memberikan ruang selebar–lebarnya pada difabel untuk mengaktualisasikan diri di dalam ranah apapun dan penerimaan masyarakat terhadap kaum difabel. Permasalahan mengenai diskriminasi harusnya sudah terselesaikan pada akhir tahun 1990-an dimana gaung reformasi pun mulai terdengar.
Persoalan diskriminasi dan stereotype ini meninggalkan pekerjaan rumah yang mungkin dari dulu hingga sekarang belum mampu dituntaskan oleh pemerintah. Akan sangat lebih baik jika pemerintah concern terhadap hal–hal kecil seperti ini. Namun seperti biasa akan sangat picik jika kesalahan hanya dibebankan pada pemerintah, masyarakat pun seharusnya mulai berbenah diri dan mencoba membuka mata agar sadar bahwa isu disabilitas mau tidak mau akan tetap menjadi isu yang harus mulai dipikirkan oleh masyarakat. Bahkan hasilnya akan terlihat lebih nyata jika masyarakat mulai membuka mata untuk menerima difabel sebagai bagian dari kehidupannya.
Sekali lagi hal ini menjelaskan bahwa persoalan diskriminasi tidak akan pernah terselesaikan jika hanya ditangani oleh pemerintah sedangkan masyarakatnya lepas tangan dan masih melakukan diskriminasi. Perjuangan mewujudkan kesetaraan terhadap difabel harus tetap dilakukan dari top (sisi pemerintah) maupun bottom (sisi masyarakat). Sehingga diharapkan terwujudnya kehidupan yang inklusif yang terus menerus digaungkan oleh ‘orang – orang pintar’ diluar sana.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)