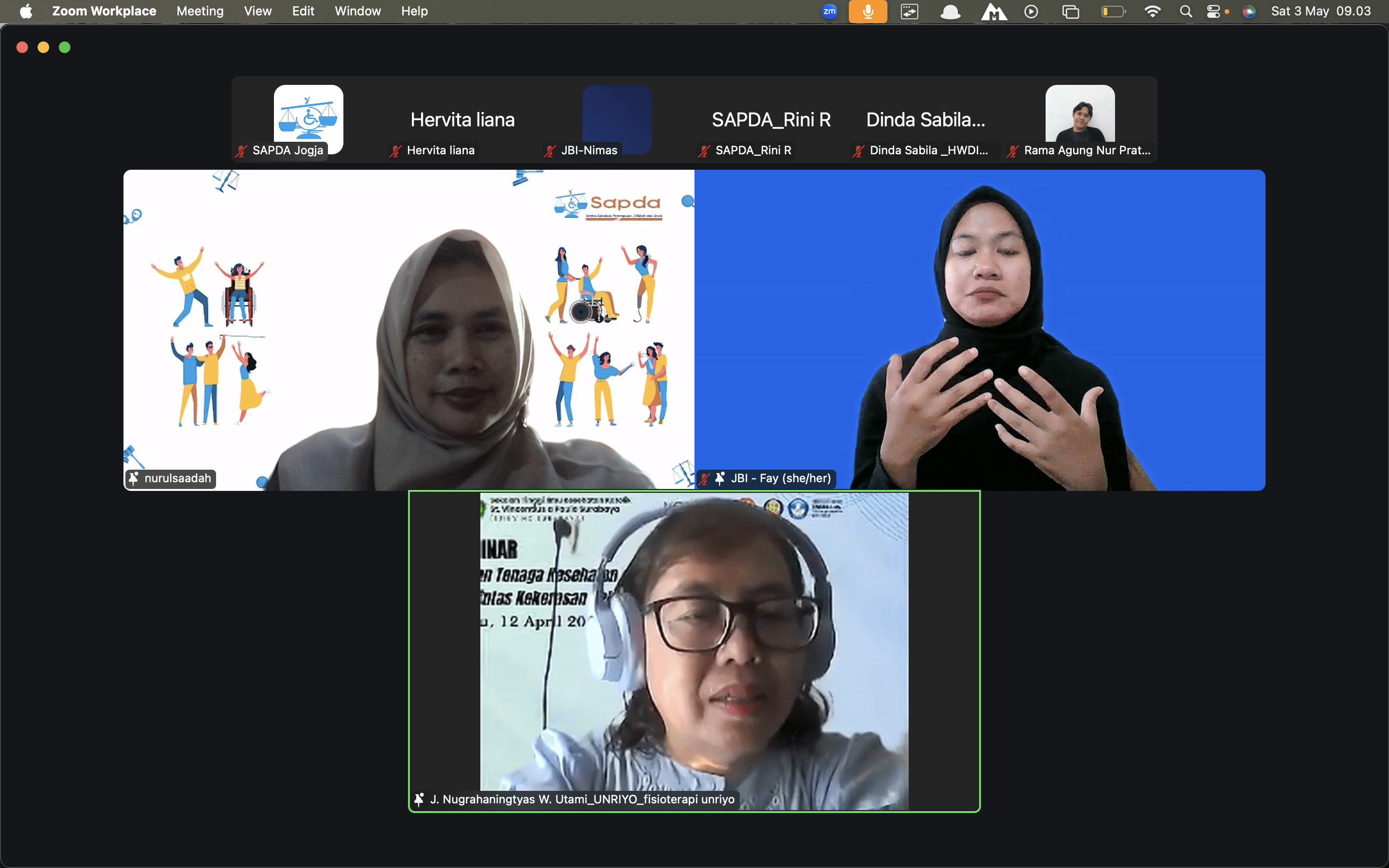Setiap orang memiliki hak untuk mengakses pengetahuan terkait isu kesehatan seksual dan reproduksi. Namun dalam realitanya banyak kelompok yang belum bisa menjangkau hak tersebut, terutama kalangan perempuan disabilitas. Ini membuat mereka rentan menjadi target kekerasan seksual.
Persoalan tersebut berhasil dibuktikan lewat penelitian bertajuk ‘Lampu Merah Kekerasan Seksual pada Disabilitas’ karya Hawa Ahda. Hawa sendiri melakukan penelitian berbasis observasi dan wawancara terhadap kelompok remaja perempuan disabilitas di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
“Ada hampir 70% mereka yang memang tidak mengetahui bentuk-bentuk dari kekerasan seksual, atau hak-hak untuk melindungi diri mereka, yang akhirnya (menimbulkan) banyak dampak yang menyebabkan hal tidak diinginkan untuk mereka,” kata Hawa, ketika memaparkan hasil penelitiannya pada diskusi ‘Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan Kekerasan’ pada Selasa (3/11) lalu.
Diskusi HKSR dan Kekerasan merupakan sesi ke-4 dari rangkaian Konferensi Nasional Hasil Riset Advokasi Berbasis Gender & Disability Social Inclusion (GEDSI). Risetnya sendiri telah berjalan sejak 8 Oktober 2019 lalu.
Dalam paparannya, Hawa menjelaskan penyebab rendahnya pemahaman mereka. Alasan utama yakni sebagian besar orang tua di Sungai Hulu Selatan masih belum menganggap penting edukasi pemahaman tentang kesehatan seksual dan reproduksi.
Bahkan sebagian besar masyarakat juga menilai bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas justru disebabkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. “Itu stigma yang masih kuat di daerah,” jelas Hawa.
Stigma inilah yang menyebabkan banyak perempuan disabilitas di Hulu Sungai Selatan sering mengalami bentuk kekerasan seksual, tanpa menyadarinya. “Pelakunya itu adalah orang-orang yang memang dekat dengan mereka. Misalnya pacar atau kekasih mereka. Atau misalnya keluarga dan teman-teman mereka,” paparnya.
Sumber pengetahuan lain, yakni institusi pendidikan, juga kurang begitu bisa diandalkan. Berdasarkan obervasinya ke sekolah-sekolah di Hulu Sungai Selatan, Hawa menemukan banyak tenaga pengajar yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi kesehatan seksual dan reproduksi kepada murid-murid disabilitasnya.
Atas dasar itu, Hawa lantas menyarankan agar otoritas pendidikan setempat untuk menyiapkan kurikulum khusus. “Karena banyak dari siswanya, anak-anak ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) ini yang tidak memahami bagaimana hak-hak kesehatan reproduksi mereka,” jelasnya.
Keadaan kian diperburuk dengan minimnya sosialisasi layanan kesehatan seksual dan reproduksi oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Hulu Sungai Selatan, terutama bagi perempuan disabilitas. “Karena jaraknya jauh. Jadi ada 80% (responden) yang mengaku belum pernah mengakses layanan ke Puskesmas sendiri,” katanya.
Atas ketiadaan akses informasi kesehatan seksual dan reproduksi dari keluarga, masyarakat, institusi pendidikan maupun kesehatan, Hawa lantas menyarankan pemerintah daerah agar menyediakan sendiri media informasinya sendiri yang dapat diakses siapa pun, termasuk penyandang disabilitas.
Masih berdasarkan hasil penelitiannya, Hawa juga menemukan banyaknya kasus kekerasan seksual perempuan disabilitas yang tidak terselesaikan. Menurutnya, pemerintah daerah Sungai Hulu Selatan belum memiliki kebijakan yang cukup memayungi dan menguatkan hak-hak korban. “Kasusnya dianggap tidak ada, tapi sebenarnya ada,” tegas Hawa.
Ketidakmampuan Hukum
Senada dengan Hawa, peneliti lainnya yakni Fadila Nur Amalia juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas lebih sulit untuk mendapatkan layanan penyelesaian hukum terkait kasus kekerasan seksual. Menurutnya, ini dikarenakan terdapat mitos-mitos salah yang beredar di kalangan aparat penegak hukum.
Mitos pertama, kata Fadila, memandang bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang tidak bisa dipercaya. “Seringkali ada anggapan, penyandang disabilitas itu ekspresinya itu berbeda dari korban kekerasan pada umumnya,” jelasnya ketika memaparkan presentasi penelitiannya yang bertajuk ”Mendambakan Peradilan yang Aksesibel terhadap Anak Disabilitas.’
Mitos kedua, mengatakan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu memberikan keterangan sebagai saksi. “Kekerasan itu dianggap semata-mata terjadi karena hasrat seksual. Padahal juga karena timpangnya relasi kuasa berdasarkan gender, umur, keadaan fisik dalam budaya yang patriarki,” jelasnya.
Mitos-mitos inilah yang juga membuat penegak hukum dinilainya kurang memiliki sensitivitas dan juga keberpihakan kepada penyandang disabilitas. “Sehingga mereka yang menjadi korban kekerasan seksual itu masih merasa didiskriminasi dan mendapatkan keadilan,” tuturnya.
Masalah tersebut pun tercermin dalam salah satu hasil penelitian Fadila. Ia sendiri melakukan penelitian berbasis studi kasus untuk memetakan kebijakan pemerintah kota Palembang dalam memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.
Menurut hasil penelitiannya, pemerintah daerah kota Palembang masih memiliki kendala dari aspek landasan hukum, ketika harus menempatkan disabilitas korban kekerasan seksual sebagai saksi. Misalnya saja, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal 1 ayat 26 dari aturan tersebut, saksi didefinisikan sebagai orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kekerasan.
“Ini sering disalahartikan. Misalnya, jika penyandang disabilitas netra menjadi korban, ada anggapan bahwa keterangannya itu tidak memadai karena kondisi fisik si korban tadi. Hal ini jelas merupakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas,” jelas Fadila.
Dalam penelitiannya, Fadila juga menemukan bahwa sejumlah instansi hukum seperti Pengadilan Negeri, Polres, dan Kejaksaan Tinggi di daerah tersebut belum memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan peradilan bagi penyandang disabilitas.
Misalnya Pengadilan Kota Palembang belum memiliki referensi untuk menentukan saksi ahli yang kompeten dalam mendampingi disabilitas korban kekerasan seksual. “Tantangan lainnya adalah belum ada SOP (Standar Operational Procedure) atau mekanisme mengenai penanganan anak dengan disabilitas,” kata Fadila.
Kendati demikian, Fadila mengapresiasi Pengadilan Kota Palembang yang berinisiatif menyediakan tenaga penerjemah, serta media informasi seputar perkembangan kasus hukum dan keputusan bagi penyandang disabilitas. “Kemudian proses peradilan juga dinilai tidak ada tekanan dalam memberikan keterangan, dan tanpa pertanyaan-pertanyaan yang menjerat,” jelasnya.
Selain itu, juga ada Woman Crisis Center (WCC) Kota Palembang yang rajin melakukan profil assesment untuk memetakan kebutuhan khusus bagi perempuan disabilitas korban kekerasan seksual, serta menyelenggrakan forum dimana korban bisa berbagi cerita. “Sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi yang terbaik,” jelasnya.
Mengubah Keadaan
Sementara itu, Nur Hidayati dari Result in Health (RIH) Belanda yang hadir sebagai penanggap begitu mengapresiasi serta berharap penelitian seperti milik Hawa dan Fadila dapat mempengaruhi kebijakan dari masing-masing daerah.
“Kalau suara mereka bisa ditangkap, suara mereka bisa diekspresikan, dan bisa menjadi masukan untuk produk-produk hukum yang disebutkan oleh teman-teman, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat bermanfaat untuk memberdayakan juga terutama perempuan dengan disabilitas.
Senada dengan Nur, Dio Ashar dari Indonesia Judicial Research Society juga mengharapkan bahwa hasil penelitian mereka mampu menjadi masukan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan teknis setiap lembaga hukum dan peradilan.
Menurutnya, aturan teknis ini penting karena setiap lembaga memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam memaknai peraturan lain yang lebih besar, sebut saja seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses peradilan.
“Karena permasalahannya dalam proses peradilan, seringkali penegak hukum itu tidak mengetahui bagaimana teknisnya jika ada penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum,” jelas Dio.
Salah satu contoh lembaga hukum yang telah memiliki aturan teknisnya sendiri adalah Pengadilan Negeri Wonosari, Yogyakarta. Perwakilan Mahkamah Agung Emie Yuliati mengatakan bahwa PN Wonosari kini telah dicontoh oleh pengadilan-pengadilan lainnya. “Tentunya ini juga berkat bantuan kerjasama bapak ibu sekalian di SAPDA,” katanya.
Lebih lajut, Emie mengatakan pihaknya juga merencanakan agar pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Perkara (SIPP) bisa memasukan data-data penyandang disabilitas. “Nantinya akan bisa diidentifikasi dari ragam disabilitas ini kebutuhan pendampingannya seperti apa,” katanya.
Ia pun mengajak SAPDA dan pihak lainnya untuk mendukung agar revisi UU Bantuan Hukum dapat mengakomodir bantuan litigasi berupa pendampingan beracara, dan non-litigasi berupa pengadaan pos bantuan hukum (Posbakum) bagi penyandang disabilitas.
“Dan ini dibiayi APBN. Seandainya, dari skenario tersebut dimasukan unsur untuk penyandang disabilitas, saya rasa akan sangat lebih mudah untuk bisa direplikasi ke pengadilan,” tutur Emie.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)