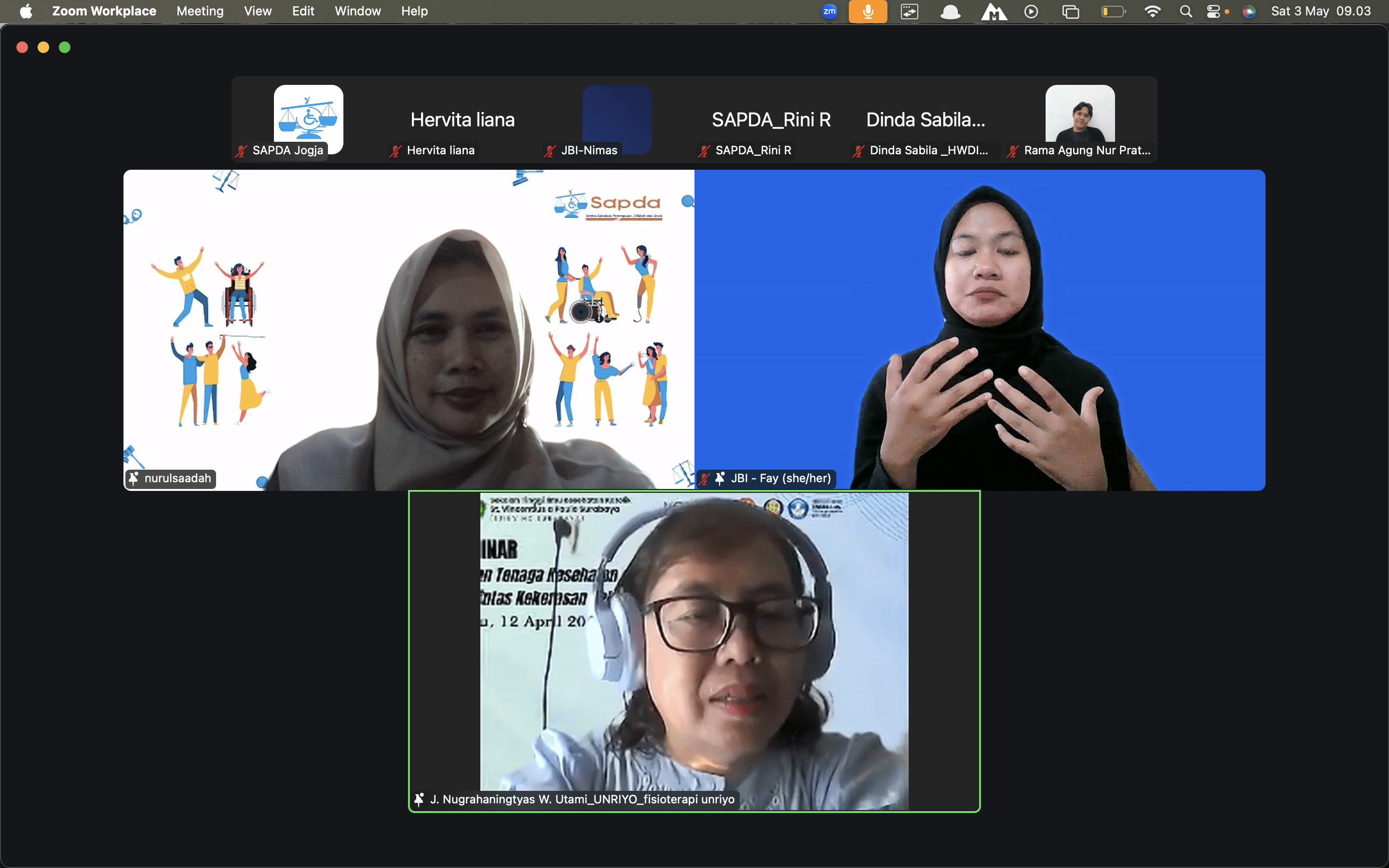Para penyandang disabilitas adalah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Karena itu, konseling sangat dibutuhkan bagi untuk meningkatkan fungsi dan perilaku mereka agar kembali adaptif terhadap lingkungan sekitar. Namun, bagi anak penyandang disabilitas, konseling seringkali sulit dilakukan karena keengganannya membagikan cerita.
Devi Riana Sari, konselor dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Yogyakarta mengatakan bahwa persoalan ini jamak terjadi kepada anak dengan maupun tanpa kondisi disabilitas. Akibatnya, kasus yang melibatkan mereka tidak jarang menguap begitu saja karena minimnya alat bukti langsung.
“Jadi yang bisa kita lakukan memberikan edukasi ke orangtuanya,” kata Devi, saat menjadi pemapar dalam acara ‘Peningkatan Kapasitas Konselor Sebaya dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Komunitas’ yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Jumat (18/12) lalu.
Persoalan ini pun diakui pula oleh Herni, ibu dengan anak penyandang disabilitas mental autisme. Ia mengatakan bahwa anak dengan autisme sulit untuk bercerita ketika misalnya menjadi korban perundungan (bullying). “Akhirnya kasusnya menguap, diselesaikan secara kekeluargaan. Menggali kasus bullying kita kesulitan,” jelas Herni, yang sekaligus perwakilan Forum Orangtua dan Masyarakat Peduli Autis Yogyakarta.
Lanjut menurut Devi, tidak mudah mendorong agar anak penyandang disabilitas mau bercerita. Perlu dibangun situasi yang membuat mereka nyaman untuk membagikan pengalamannya di masa sekarang dan di masa lalu. “Penting menggali bukan saja pengalaman saat ini, tapi apa yang sebelumnya dia alami. Ini menyangkut data,” jelasnya.
Untuk membuat anak penyandang disabilitas merasa nyaman, kata Devi, salah satunya konselor harus memposisikan diri setara sebagai teman sebaya bagi sang anak. “Ketika tidak ada jarak antara klien dan konselor, mereka akan bercerita,” jelas Devi.
Hal itu juga didukung oleh Maya, seorang ibu dengan dua anak penyandang disabilitas intelektual grahita. Dalam acara, ia menuturkan bahwa anak dengan grahita sulit bercerita terutama ketika menghadapi masa pubertas. Saat itu terjadi, dirinya harus membuka hati dan pikiran agar putra dan putrinya mau bercerita.
“Saya juga ajak setiap hari dengan Bahasa sederhana agar anak saya perempuan bisa cerita ke saya. Untuk dia (mau) cerita, kadang saya butuh (bantuan) orang lain juga. Anak saya introvert. Jadi ketika dia mau cerita ke saya, saya senang,” ungkap Maya yang sekaligus merupakan perwakilan Mutiara Grahita.
Peningkatan emosi yang signifikan juga terjadi setiap anaknya menghadapi masa haid. Kala itu terjadi, Maya memilih untuk diam dan membiarkan hingga situasi membaik. “Daripada dia marah, saya marah, dan tidak ada jalan keluar, jadi saya diam dulu. ketika dia tenang, mau bercerita baru saya ajak bercerita. Benar memang keadaan harus kondusif,” tuturnya.
Cara yang dilakukan Maya juga rajin diterapkan Devi kepada para kliennya. Misal, dalam satu pengalamannya saat menghadapi remaja disabilitas dengan depresi berat, Devi harus diam dan membiarkannya menangis selama 15 menit sebelum bisa membuka obrolan. “Memang tidak mudah agar dia bercerita. Kita butuh skill khusus untuk menggali,” katanya.
Solusi lain kemudian ditawarkan Supri dari Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Yogyakarta. Berdasarkan pengalamannya mengasuh murid grahita, ia menyarankan agar konselor lebih mengedepankan pendekatan mengalihkan perhatian ketimbang mengarahkan. “Karena anak-anak seperti itu memang sulit diberi tahu benar salahnya,” ujarnya.
Melengkapi Supri, Devi menyebut metode tersebut sebagai pembiasaan atau modelling, yakni mengemas nilai-nilai baik ke dalam kebiasaan sehari-hari. “Ketika anak dilarang main handphone, ibunya tidak main handphone juga. Kita butuh tenaga ekstra dan waktu panjang untuk mereka, sehingga butuh waktu juga lebih lama,” jelasnya.
Pendekatan modelling tersebut, kata Devi, akan mampu mengubah perilaku anak jika dilakukan secara kontinu. “Ketika ibu sudah memberikan edukasi ke anak, tapi perilaku tidak berubah, berarti orang yang ada di lingkungan anak itu penyebabnya. PR-nya adalah edukasi ke orangtua,” paparnya.
Sebagai informasi, diskusi ini diinisiasi oleh hola Woman Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA. Fatum Ade, anggota dari divisi tersebut, mengatakan acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teman-teman konselor sebaya dalam memberikan konseling psikologi kepada perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
Acara turut dihadiri perwakilan Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Sigrak), serta sejumlah organisasi penyandang disabilitas, seperti Komunitas Teater Bertubuh Mini; Paraplegi; Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) wilayah Kota Yogyakarta; Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis); Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Yogyakarta, dan Wahana Keluarga Cerebal Palsy.
Para peserta antara lain mendapatkan materi tentang definisi konseling, teknik konseling, tahapan dalam proses konseling, etika dalam praktik konseling, serta keterampilan dasar yang perlu dimiliki para konselor.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)