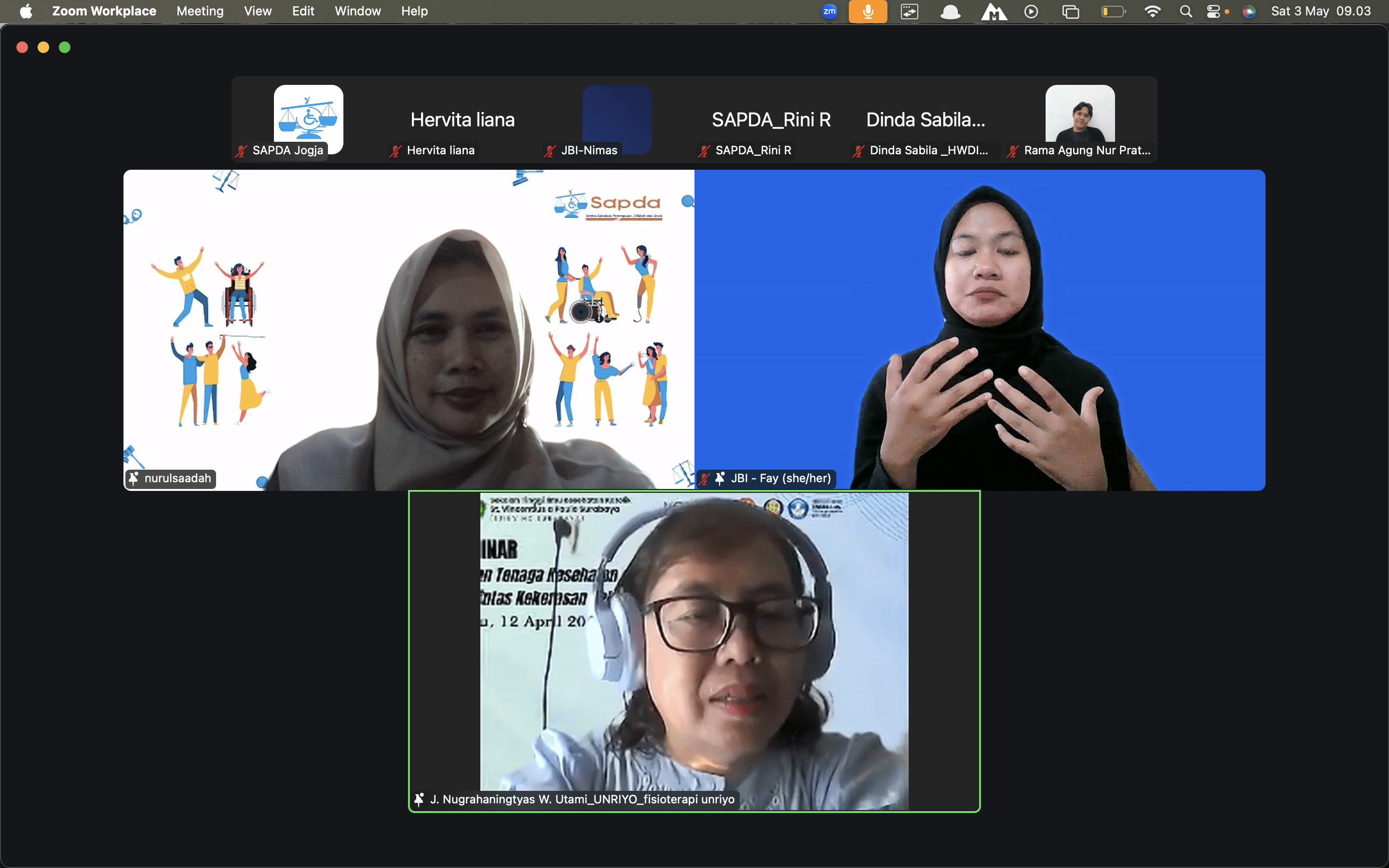Perempuan penyandang disabilitas adalah kelompok yang tersubordinasi dan sulit mendapatkan ruang eksistensi di masyarakat. Karena itu, peran media sangat penting menjadi wadah untuk mengisi ketiadaan ruang suara mereka.
Namun seringkali konten media memihak pada cara pandang mayoritas yang keliru dalam memaknai perempuan penyandang disabilitas. Ini menyebabkan perempuan penyandang disabilitas mendapatkan representasi yang salah dalam layar kaca.
Fauziah Ismi, salah satu periset dalam program Riset Advokasi Berbasis Gender & Disability (GEDSI) mengatakan bahwa representasi yang salah tentang perempuan penyandang disabilitas marak ditemui pada tayangan sinetron bertema ‘azab’ di televisi.
“Saya melihat banyak sinetron yang membawa isu disabilitas dalam hubungannya dengan azab, khususnya bagi perempuan. Karena perlakuan dosa, maka wajib hukumnya mereka terkena suatu hal yang akhirnya membuat lumpuh. Sehingga dalam konteks ini disabilitas dianggap sebagai suatu dosa perempuan terhadap laki-laki,” katanya.
Dalam diskusi bertajuk Pemberdayaan Perempuan Disabilitas dan Kebijakan yang berlangsung pada Kamis (29/10) lalu, Fauziah menyampaikan bahwa representasi tentang tubuh perempuan penyandang disabilitas dalam tayangan sinetron azab hampir selalu sama dan diulang-ulang.
“Pertama bahwa tubuh perempuan penyandang disabilitas daksa dianggap sebagai double monster. Satu dianggap menjijikan, satu dianggap aseksual. Menjijikan karena dianggap lemah, dianggap tidak berdaya, sangat bergantung,” jelas Fauziah.
Kedua, menurut Fauziah, kondisi kedisabilitasan perempuan dibingkai sebagai sesuatu yang timbul secara logis atas kesalahannya kepada laki-laki. “Menurut saya itu sangat menyedihkan, mengingat disabilitas dimaknai sebagai suatu pelemahan terhadap perempuan itu sendiri,” katanya.
Menurutnya, cara-cara pandang tersebut kini sudah terlalu kuat dan mengakar di dalam masyarakat. “Sehingga yang jadi diingat terus oleh kita semua adalah penggambaran-penggambaran yang tidak layak tentang perempuan penyandang disabilitas,” kata Fauziah.
Media Digital sebagai Harapan
Karena sulit untuk mendapatkan ruang representasi adil di media komvensional, perempuan penyandang disabilitas bisa memanfaatkan media digital untuk menciptakan representasi tandingan tentang kelompok mereka. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat vlog kecantikan.
Dari hasil risetnya yang bertajuk Melawan Representasi Disabilitas dengan Make Up, Fauziah menyarankan sejumlah teknik yang bisa digunakan perempuan penyandang disabilitas ketika ingin menyuarakan kepentingan lewat instrumen vlog kecantikan.
Pertama adalah elaborasi. Dalam teknik ini, perempuan penyandang disabilitas sebagai subjek utama dari vlog bisa menyisipkan ajakan untuk menyuarakan isu disabilitas ketika melakkan aktivitas kecantikan. “Ini bisa menjangkau penonton perempuan disabilitas maupun non-disabilitas,” jelas Fauziah.
Kedua, adalah itentifikasi dialog, yakni dimana perempuan penyandang disabilitas bisa menceritakan perjalanan perubahan tubuhnya kepada audiens. “Jangan malu mengatakan bahwa ‘ya saya disabilitas daksa, perjalanan tubuh saya seperti ini, pengobatan yang saya lakukan seperti ini. Saya menerima diri saya apa adanya dan ada perasaan bangga bahwa saya telah melewati itu semua,” tutur Fauziah mencontohkan.
Menurut Fauziah, intentifikasi dialog dibutuhkan keberanian untuk membuka luka dan perjuangan tubuh perempuan penyandan disabilitas di masa lalu. “Penonton akan diarahkan untuk memahami kehidupan disabilitas yang sama kok seperti teman-teman yang lain, bahwa mereka berteman, memiliki pekerjaan, karya, cita-cita yang harus kita semua dukung,” jelas Fauziah.
Kampanye Alternatif Melawan Patriarkis
Setuju dengan Fauziah, Rubby Emir dari Kerjabilitas memandang bahwa apa yang dilakukan para beauty vlogger perempuan penyandang disabilitas bisa menjadi bentuk kampanye alternatif untuk menyuarakan isu disabilitas.
“Dalam arti ini bisa menjadi model-model baru yang memberikan khazanah baru tentang bagaimana isu disabilitas bisa menjadi isu arus utama, kemudian didorong untuk diadvokasi supaya tercipta sebuah negara atau society yang inklusif,” kata Rubby.
Rubby pun lantas berharap ada lebih banyak peneliti yang bisa menangkap upaya-upaya populer kelompok marjinal dalam memperjuangkan kepentingan mereka, seperti vlog kecantikan para perempuan penyandang disabilitas itu sendiri.
Namun, ia menyorot adanya bias budaya patriarkis dalam penggunaan vlog kecantikan sebagai alat kampanye. Bias ini datang dari definisi kecantikan mainstream yang diadopsi dari cara pandang laki-laki. “Kecantikan yang didefinisikan secara mainstream itu kan kecantikan dari sistem model laki-laki,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yustisia Arief dari Advokasi Disabilitas Inklusi (Audisi) mengatakan bahwa budaya patriarkis itulah yang selama ini telah mereduksi posisi perempuan yang sejatinya memiliki peran dalam pembangunan, menjadi hanya sebagai mahluk domestik.
“Untuk perempuan disabilitas, ditambah lagi dengan pandangan yang mempertanyakan apakah ia mampu mengurus keluarga dengan kondisi disabilitas yang dimilikinya? Apakah ia mampu mendidik anak-anak, dan mengurus pasangannya?” jelas Yustisia.
Menurut Yustisia, subordinasi terhadap perempuan penyandang disabilitas juga terlegitimasi negara lewat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti yang diketahui, UU ini menjadikan cacat tubuh sebagai justifikasi peceraian.
“Walau di UU tersebut ada pasal yang menjelaskan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri itu sama, tetapi kembali direduksi dengan peran yang mengesampingkan pengarusutamaan gender, yaitu bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga,” katanya.
Sementara itu, periset lain yakni Umi Salamah, dari hasil penelitiannya bertajuk ‘Efektifkah Pemberdayaan Perempuan Disabilitas di Kabupaten Kediri?’ ia menyarankan agar setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan yang menjangkau kebutuhan khusus hak perempuan penyandang disabilitas.
“Permasalahan perempuan disabilitas sangat kompleks. Tapi program-program pemerintah belum bisa menjangkau seluruh perempuan disabilitas. Padahal mereka lebih rawan dalam keamanan dari sisi fisik dan tantangan mobilitas, sehingga memerlukan pendampingan dalam melakukan kegiatan yang diadakan pemerintah,” jelasnya.
Umi melanjutkan, bahwa lewat pemerintah pulalah, keberadaan perempuan penyandang disabilitas dipandang penting oleh masyarakat umum. “Untuk mengubah pola pandang masyarakat terhadap disabilitas, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam program kegiatan untuk mengenal lebih dekat mengenai dunia disabilitas,” katanya.
Diskusi ini merupakan sesi ke-3 dari rangkaian Konferensi Nasional Hasil Riset Advokasi Berbasis Gender, Disability, & Social Inclusion (GEDSI). Risetnya sendiri telah dilangsungkan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Anak, dan Difabel (SAPDA) Yogyakarta sejak 8 Oktober 2019 lalu.
Hadir pula dalam diskusi, yakni Ding Peng dari Wuhan University yang membagikan peran komunitas akademis internasional dalam memperjuangkan hak perempuan penyandang disabilitas di Asia, serta pengajar dari UIN Sunan Kalijaga Ro’fah Makin yang memaparkan metodologi penelitian berbasis GEDSI.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)