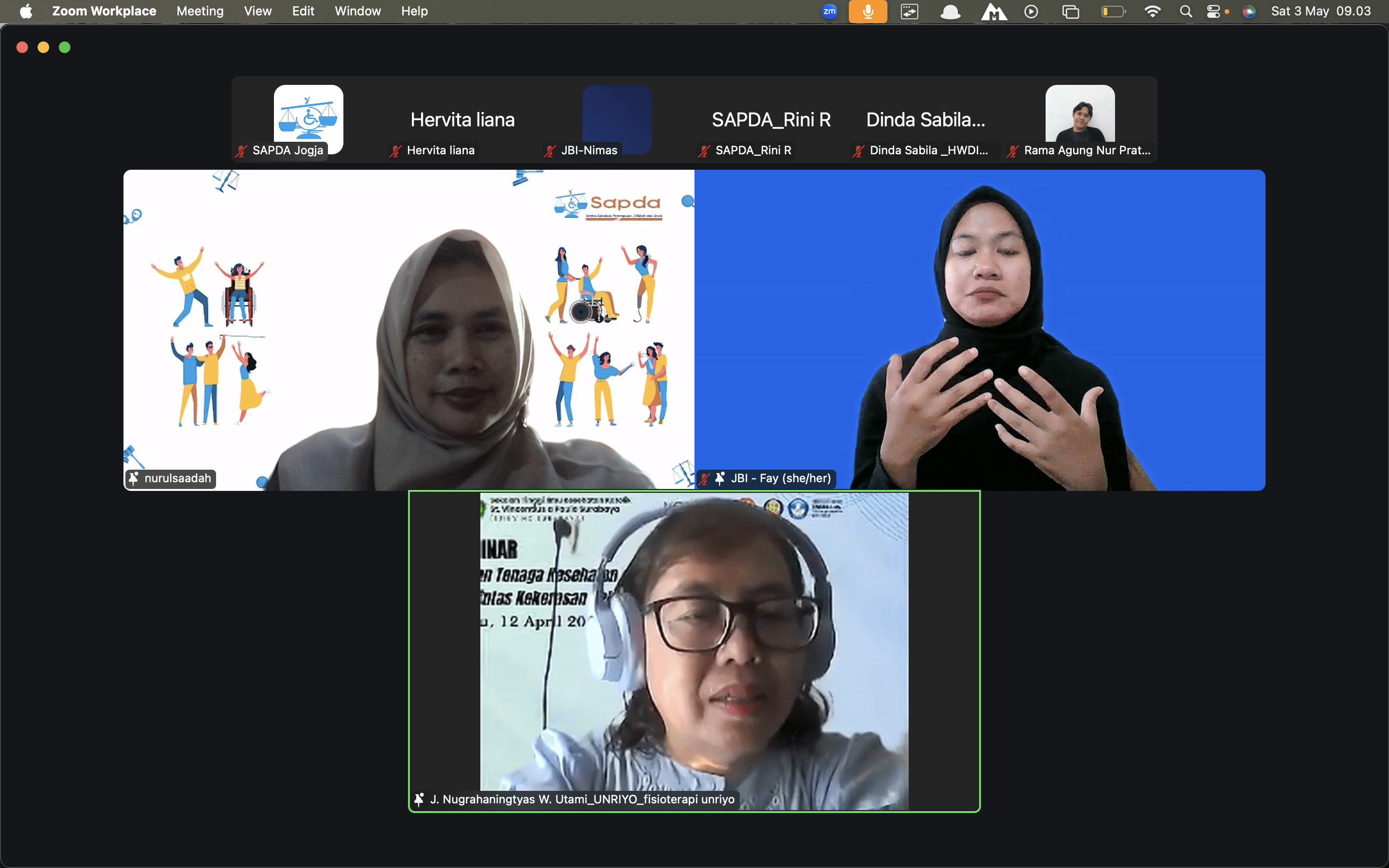Para penyandang disabilitas dan orang dengan HIV/AIDS (Odha) sama-sama merupakan kelompok marjinal. Keduanya menghadapi ancaman kerentanan yang serupa, mulai dari stigma negatif, peminggiran, dan tidak tersentuh layanan aksesibel.
Perwakilan divisi Gender Equality, Disability, & Social Inclusion (GEDSI) dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Sholih Muhdlor menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dan Odha sama-sama dipandang negatif oleh masyarakat. Misalnya dianggap terkutuk, atau punya kesalahan masa lalu.
“Ini satu hal yang bisa kita tarik benang merah bersama-sama, bahwa ada stigma negatif di antara mereka berdua,” kata Sholih, saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Solidaritas 10 Tahun Menuju Akhir AIDS 2030 Senin (1/12).
Karena stigma negatif itulah, dua kelompok tersebut sama-sama pula mengalami peminggiran. Terdapat kecenderungan perilaku yang sama dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan Odha, yakni menjauhkan diri dan takut akan penularan.
“Padahal kita sama-sama tahu bahwa disability bukan penyakit menular, atau bahkan bukan penyakit sama sekali. Dan HIV/AIDS itu penularannya juga punya media yang sangat spesifik, yang itu sebetulnya sangat bisa kita hindari,” jelas Sholih.
Kedaaan kemudian kian diperburuk dengan minimnya layanan yang aksesibel bagi kebutuhan khusus mereka. Sholih menuturkan bahwa regulasi dan kapasitas di tingkat Dinas Kesehatan belum mampu memungkinkan layanan khusus HIV/AIDS karena kurangnya tenaga kesehatan, ahli, dan relawan.
“Maka kemudian teman-teman penyandang disabilitas dan teman-teman odha ini juga semakin tidak mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, baik layanan informasi, kesehatan, atau pendampingan dan pemulihan,” jelas Sholih.
Selain itu, layanan pemulihan psikologis bagi mereka juga belum banyak. Padahal, menurut Sholih, pemulihan psikologis membantu penyandang disabilitas dan Odha dalam meningkatkan penerimaan diri mereka. Penerimaan inilah yang turut menentukan keberhasilan pengobatan kesehatan.
“Proses pengobatan, penyembuhan, untuk meminimalkan agar disabilitasnya tidak menjadi lebih parah, itu tidak akan pernah bisa terjadi dengan baik dan sukses ketika secara psikologis dia belum ada pada proses penerimaan,” tuturnya.
Stigma, peminggiran, dan minimnya layanan kesehatan yang aksesibel pada akhirnya membuat penyandang disabilitas dan Odha seringkali hidup dalam lingkaran pergaulan yang tertutup. “Nah lingkaran yang tertutup ini bagi teman-teman disabilitas bagaimana penularan HIV lebih cepat,” kata Sholih.
Kerentanan yang lebih berlapis dialami penyandang disabilitas yang sekaligus Odha. Dokter Sumardi, spesialis penyakit dalam dari tim HIV/AIDS Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito menjelaskan sejumlah faktor yang membuat penyandang disabilitas rentan menjadi pasien HIV/AIDS.
Faktor pertama adalah lingkungan luar yang mendorong penularan HIV/AIDS. Misalnya saja, penyandang disabilitas di kampung yang warganya marak melakukan praktik injeksi narkoba. “Lingkungan tempat tinggalnya atau perilaku extraterestialnya sudah tidak aman,” kata Dokter Sumardi.
Faktor kedua, adalah kekerasan seksual. Menurut Dr. Sumardi, penyandang disabilitas setidaknya pasti pernah menerima pelecehan seksual satu hingga dua kali dalam hidupnya. “Nah ini yang kadang-kadang tidak tercatat. Yang tercatat aja enggak sedemikian besar, barangkali yang tidak tercatat lebih banyak lagi,” katanya.
Persoalan tersebut khususnya berlaku bagi penyandang disabilitas mental intelektual yang lebih rentan menjadi sasaran pelaku pelecehan seksual. “Nah, kondisi (disabilitas) seperti inilah yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual,” jelas Dokter. Sumardi.
Faktor ketiga, adalah ketiadaan akses bagi penyandang disabilitas terhadap edukasi kesehatan seksual. Mereka umumnya tidak memperoleh pendidikan formal, dimana pengetahuan paling dasar tentang isu ini berasal. “Kita saja yang berada di area tanpa disabilitas barangkali masih juga belum seratus persen terjangkau pendidikan reproduksi,” ujar Dokter Sumardi.
Sumber alternatif lainnya, sebut saja seperti pelayanan kesehatan, juga seringkali tidak aksesibel. Sulit untuk menemukan leafet tentang isu kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah bagi penyandang disabilitas. “Terutama yang tunanetra, karena tidak pernah ada leaflet dalam bentuk braille,” katanya.
Tak hanya edukasi, layanan pengobatannya pun umumnya juga mudah diakses bagi penyandang disabilitas karena ketiadaan fasilitas-fasilitas tambahan yang mampu memenuhi kebutuhan khusus mereka. “Bagaimana tunanetra harus bisa jalan sendiri. Turun dari bus, pergi ke klinik, bertemu dokternya, ketemu tenaga kesehatan tanpa dibantu,” ujar Dr. Sumardi.
Faktor terakhir, adalah medis. Terkhususkan bagi penyandang disabilitas intelektual, mereka tidak bisa selalu mengonsumsi obat ARV karena berbentrok dengan obat jiwanya. “Terjadi interaksi obat, kemudian hasilnya pasien mengamuk terus. Tenaga kesehatan dalam memberikan pengobatan perlu melihat kondisi obat-obatnya,” lanjut Dokter Sumardi.
Keadaan lantas kian sulit dengan datangnya pandemi Covid-19. Juru Bicara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk Penanganan Covid 19 Berty Murtiningsih mengatakan bahwa pandemi membuat pencegahan dan penganggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta menjadi penuh tantangan.
Tantangan yang utama adalah kewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan dalam memberikan pengobatan. “Juga kita saat ini memang untuk tenaga kesehatan sedang terkonsentrasi pada covid. Jadi, ini yang perlu kita cari solusinya,” kata Berty.
Selain itu, juga terdapat persoalan perihal ketersediaan ARV bagi para penyintas HIV/AIDS. “Karena keterbatasan ini kita harus bisa memberikan layanan yang efektif dan efisien. Ini agak menjadikan permasalahan saat harus mendistrubsikan sesuai kebutuhan,” terang Berty.
Tantangan-tantangan tersebut terlihat dari adanya penurunan angka jangkauan tes HIV/AIDS di DIY. “Untuk tahun 2020 di awal-awal kita bisa mencapai cakupan yang lumayan. Tapi begitu pandemi ini berjalan, kita agak kesulitan dalam mempertahankan capaian tes HIV kita,” tutur Berty.
Menurut data Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2020 tes HIV/AIDS sukarela hanya menjangkau 3.733 orang. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 7.334 orang. Menjelang akhir tahun, jumlah orang yang sukarela dites juga menurun. Terakhir kali Oktober lalu, tes tersebut hanya menyentuh 133 orang. Sedangkan angka tertinggi berada di bulan Februari yakni 761 orang.
Penurunan juga terjadi pada tes HIV/AIDS insiatif petugas kesehatan. Tes ini hanya menjangkau 32.213 orang, lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 53.496 orang. Pada tes ini, penurunan terlihat lebih buruk, dimana pada November lalu tes hanya menentuh 18 orang. Sedangkan angka tertinggi berada di bulan Februari yakni 5.183 orang.
Ada pun pada 10 tahun terakhir, jumlah Odha di DIY mencapai 4.643 untuk HIV dan 1.401 untuk AIDS. Selain itu, pemerintah DIY juga menemukan 23 penyandang disabilitas yang sekaligus menjadi odha, terdiri dari 16 tunawicara dan tunarungi, 1 tunanetra, 2 disabilitas fisik, dan 1 disabilitas intelektual.
Turut hadir pula dalam seminar ini, yakni Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudana. Huda lantas memberikan masukan dan evaluasi terhadap regulasi yang berhubungan dengan penyandang disabilitas milik Pemerintah DIY.
Menurutnya, dari sekian banyak perturan yang ada, hanya Peraturan DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah berjalan efektif. “Dari segala macam regulasi yang ada, banyak sekali perda dan pergub ini yang belum telaksana dengan sepenuhnya. Efektifitasnya masih belum terlalu baik,” katanya.
Hal itu menurutnya terlihat dari belum sampainya aksesibilitas ke level desa. Padahal, menurutnya membangun fasilitas inklusif cukup murah. “Cukup lah dia bisa pindah dari lantai dua ke lantai satu. Dikasih RAM kecil satunya juga enggak sampai 2 juta. Ini sesuatu hal yang murah tapi belum juga dilakukan,” jelasnya.
Huda pun juga menyorot Perda DIY Nomor 12 tahun 2012 tentang penanggulangan HIV/ADIS yang dinilainya sudah kurang relevan. Ia mengatakan bahwa perda tersebut harus direvisi ke arah sosialisasi preventif. “Perda harus mampu memberikan payung hukum sosialisasi secara gamblang hingga kelompok-kelompok agama dan dasawisma,” tegasnya.
Webinar ini diselenggarakan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pemerintah DIY. Seperti yang diketahui, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penganggulangan HIV/AIDS manargetkan 0 infeksi, 0 kematian, dan 0 diskriminasi pada tahun 2030.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)