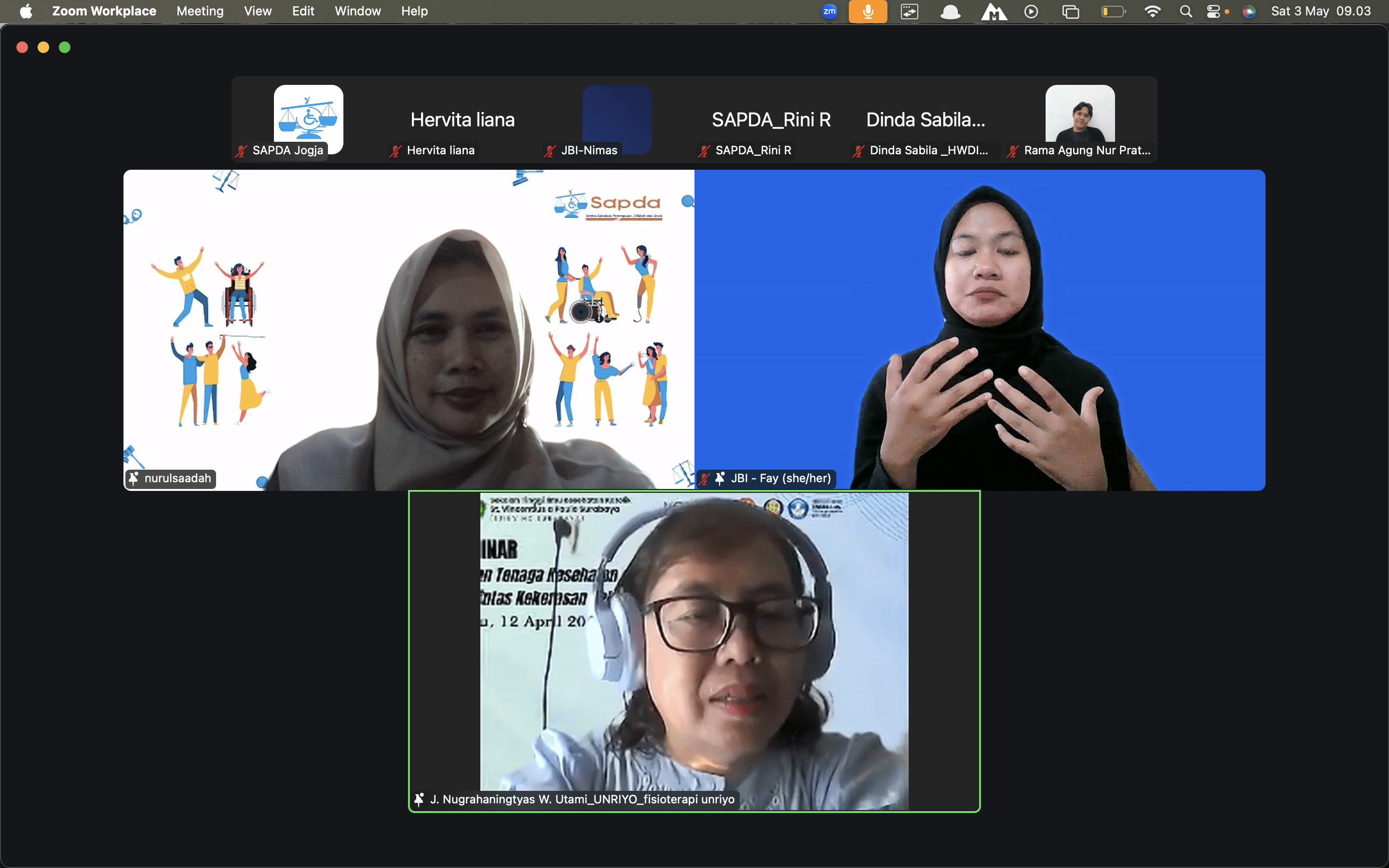Pembuatan aturan-aturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menyisakan ruang kosong bagi partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas mendesak pemerintah untuk memastikan perlibatan yang bermakna bagi organisasi disabilitas dalam pembahasan dan penyusunan peraturan turunan UU TPKS.
“Tidak terbukanya informasi terkait draft resmi seluruh aturan turunan, dan tidak dilibatkannya Jaringan Masyarakat Sipil dan Jaringan Disabilitas pada Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) serta seluruh proses lainnya adalah tindakan pencideraan demokrasi oleh KemenPPPA dan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat,” kata Koordinator Advokasi Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Indonesia, Fatum Ade, melalui rilis media dalam konferensi pers yang dikoordinasi PJS Indonesia pada Senin (19/6).
Ade menegaskan partisipasi masyarakat merupakan syarat dari salah satu prinsip pemerintahan yang demokratis, yakni adanya keterbukaan dan transparansi dalam semua proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, baik perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan dan penetapan. “Organisasi masyarakat dan organisasi disabilitas harus dilibatkan secara penuh, bukan hanya datang dan hadir, tetapi juga turut memberikan saran dan masukan dalam forum-forum yang diselenggarakan pemerintah,” katanya.
Senada dengan Ade, Koordinator Rumah Cakap Bermartabat Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (RCB SAPDA), Arini Robi Izzati, mengingatkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas sangat penting agar isi aturan turunan UU TPKS sebisa mungkin memotret pengalaman pendampingan korban. “Aturan teknis yang menerjemahkan UU TPKS tanpa berbasis pengalaman korban, hanyalah seperti macan ompong. Aturan teknis sangat diperlukan untuk menjamin keadilan bagi penyandang disabilitas di lapangan,” katanya.
Manajer Program dan Advokasi Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Purwanti, mengatakan, upaya menjamin perlibatan yang bermakna bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan melaksanakan diskusi kelompok terarah yang ditujukan secara khusus untuk membahas teknis perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. “Perlu ada focus group discussion tersendiri, karena isu kekerasan pada penyandang disabilitas ini rentangannya sangat lebar. OPD harus dilibatkan dalam forum pembahasannya,” tegasnya.
Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 25 dan 26 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2023, pemerintah menyepakati ada tujuh naskah regulasi pelaksana UU TPKS yang harus disahkan hingga Juni tahun ini, terdiri dari tiga rancangan Peraturan Pemerintah dan empat rancangan Peraturan Presiden.
Tiga Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah rancangan PP tentang Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; rancangan PP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan rancangan PP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Sedangkan empat Peraturan Presiden yakni rancangan Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat; rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; serta rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Lembaga Penyedia Layanan berbasis masyarakat.
Purwanti mengatakan regulasi-regulasi pelaksana di atas sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum terkait penanganan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan, termasuk proses acara pidana. “Aturan yang ada saat ini masih bersifat himbauan, misalnya surat edaran, yang daya ikatnya lemah. UU TPKS telah mengatur 10 pasal tentang disabilitas, tetapi pasal-pasal itu masih disharmonis dengan kebijakan-kebijakan yang lain, sehingga perlu diatur secara sistemik dalam kebijakan turunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas menilai aturan-aturan tersebut penting untuk disahkan mengingat masih banyaknya hambatan dalam praktik-praktik pendampingan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, seperti kurang optimalnya penyediaan akomodasi yang layak, masih banyaknya aparat penegak hukum tanpa perspektif disabilitas, adanya kerentanan yang lebih besar terjadinya tindak kekerasan seksual di panti sosial dan rumah sakit jiwa, serta kurangnya perlindungan bagi pendamping disabilitas.
Hambatan dalam penyediaan akomodasi yang layak salah satunya diceritakan oleh Rumah Cakap Bermartabat SAPDA. Arini bercerita bahwa lembaga layanan dan aparat penegak hukum masih tergagap-gagap berhadapan dengan penyandang disabilitas, sehingga proses layanan yang diberikan jauh dari keadilan. Selain itu, penyediaan akomodasi yang layak juga dilakukan tanpa asesmen yang mendalam terhadap kebutuhan individual penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.
“Akomodasi yang layak adalah jaminan pemenuhaan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, jaminan kekerasan. Akomodasi yang layak menempel pada setiap proses, bukan hanya pada proses peradilan. AYL adalah pengakuan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum, tidak hanya pada proses peradilan. Karena itu, penyediaannya perlu memastikan partisipasi yang bermakna bagi penyandang disabilitas,” kata Arini.
Kurang optimalnya penyediaan akomodasi yang layak tak terlepas dari hambatan lain, seperti minimnya perspektif disabilitas. Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Pusat, Revita Alvi menuturkan ketiadaan perspektif disabilitas pada aparat penegak hukum dan petugas penyedia layanan berdampak pada pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.
Revita mencontohkan, masih banyak aparat penegak hukum yang menolak peran serta pendamping disabilitas dalam proses peradilan. “Padahal, pendamping disabilitas adalah bagian dari akomodasi yang layak. Pendamping membantu penyandang disabilitas lebih percaya diri dan bersedia melalui proses peradilan,” katanya.
Sebagai informasi, konferensi pers ini dilakukan sebagai desakan Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah untuk membuka ruang seluas-luasnya dalam seluruh proses penyusunan aturan pelaksana UU TPKS. Beberapa rancangan Aturan Pelaksana ini kabarnya sudah akan masuk tahap harmonisasi sehingga di bulan Juni 2023 dapat disahkan.
Proses penyusunan dan pembahasannya seluruh aturan pelaksana ini jauh dari transparan dan tanpa adanya partisipasi bermakna dari kelompok berkepentingan. Bahkan sampai saat ini, draft resmi terkait aturan-aturan pelaksana tersebut belum pernah di buka kepada publik. Tindakan ini jelas melanggar Pasal Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengamanatkan dalam setiap proses penyusunan aturan haruslah terbuka dan transparan.
Sebanyak 11 lembaga tergabung dalam Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas, yakni Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJS), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anaka (SAPDA), OHANA Indonesia, Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN), Yayasan Pedulis Sindroma Down Indonesia (YAPESDI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUAD), Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur, Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (CIQAL), dan Rumah Disabilitas Sriwijaya (RDS).




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)