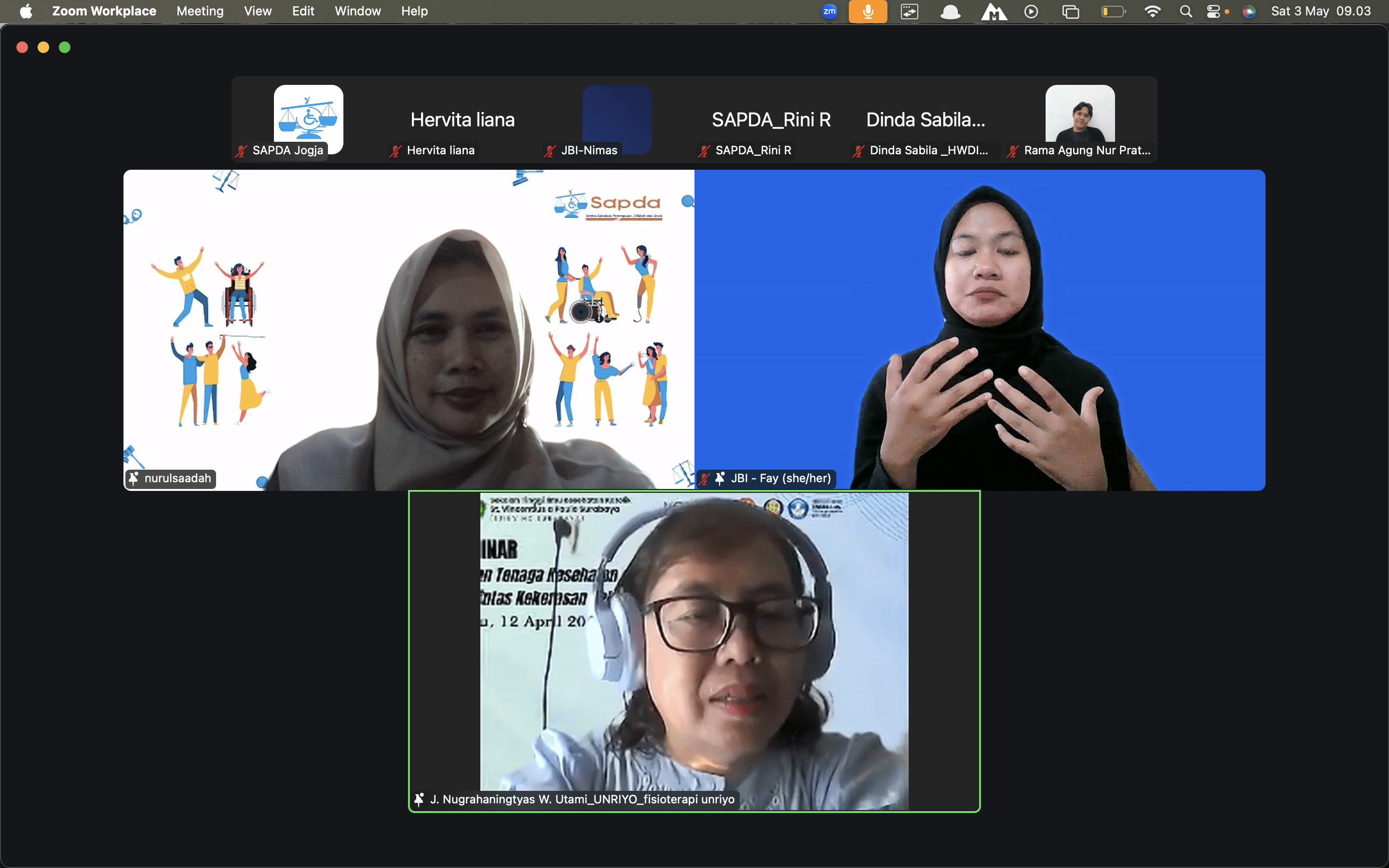Pemenuhan hak perempuan dan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di level institusi pengadilan masih menghadapi tantangan dan hambatan. Peraturan Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar berbagai upaya penyediaan akomodasi yang layak, penerapan penilaian personal, hingga memastikan sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berperspektif disabilitas, dapat berjalan lebih optimal.
Situasi ini menjadi sorotan dalam kegiatan Pembahasan Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) bersama Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) pada Jumat (19/5) lalu.
Kyntan Gita Palupi dari Women Disability Crisis Center (WDCC) SAPDA mengatakan tak jarang masih ada kasus penyandang disabilitas disabilitas berhadapan dengan hukum yang masuk tanpa kelengkapan penilaian personal. Menurutnya, hal ini terjadi biasanya karena hambatan kedisabilitasan baru teridentifikasi di tengah proses pemeriksaan perkara.
“Permasalahan lain adalah, ketika hakim meminta untuk melakukan penilaian personal kepada kejaksaan, terkadang kejaksaan tidak memenuhi permintaan tersebut. Mereka menganggap bahwa pengaturan mengenai penilaian personal berada di SK Dirjen Badilum, Badilag, atau Badimiltun, sehingga mereka tidak mau melaksanakannya karena dianggap bukan wewenang kejaksaan,” ujarnya ketika mempresentasikan draft Raperma.
Ketiadaan penilaian personal, lanjut Kyntan, tentunya berdampak pada penyediaan akomodasi yang layak. Ia menuturkan, mayoritas penyediaan akomodasi yang layak oleh pengadilan masih berpusat pada sarana prasarana, itu pun sebagian besar hanya di level Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini berdasarkan temuan pemantauan terhadap pengadilan inklusif dampingan SAPDA yang dilakukan pada 2021 dan 2022.
“Ketika penyediaan akomodasi yang layak tidak diberikan dalam seluruh tahapan persidangan, itu akan menghambat proses pemeriksaan penyandang disabilitas itu sendiri. Misal dalam kasus kekerasan seksual yang didampingi SAPDA di Bantul, korban anak penyandang disabilitas membutuhkan alat peraga, namun di ruang persidangan tidak tersedia akomodasi itu,” tegasnya.
Tak hanya itu, ketimpangan penyediaan akomodasi yang layak juga terlihat antar pengadilan di berbagai daerah. “Misalnya terkait dengan juru bahasa isyarat. Di Jogja mungkin akan sangat mudah untuk mengakses juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas Tuli. Tapi akan berbeda dengan misalnya Jawa Tengah, dimana sangat susah mengakses akomodasi serupa,” lanjutnya.
Berdasarkan situasi-situasi tersebut, menjadi sangat penting agar mekanisme penyediaan akomodasi yang layak, baik sarana dan prasarana maupun layanan, termasuk penerapan penilaian personal, mendapatkan dukungan legitimasi hukum dengan diatur lebih dalam oleh regulasi setingkat peraturan Mahkamah Agung.
Akses Peningkatan Kapasitas bagi Hakim
Perma ini, tutur Kyntan, harapannya juga bisa menjadi dasar hukum bagi Hakim untuk bisa mendapatkan akses peningkatan kapasitas tentang isu disabilitas. Masih berdasarkan temuan pemantauan pada 2021 dan 2022, peserta pelatihan terkait pengadilan inklusif yang diselenggarakan oleh SAPDA masih didominasi oleh petugas pelayanan.
“Untuk peningkatan pemahaman terkait dengan isu disabilitas juga penting diberikan kepada Hakim, karena Hakim juga yang akan menangani penyandang disabilitas secara langsung, berinteraksi, memahami hambatan, memahami kebutuhan dan sebagainya. Hakim juga perlu untuk memahami hal-hal tersebut,” tandasnya.
Ia menuturkan, peningkatan kapasitas ini juga penting untuk mengikis stigma terhadap penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Stigma tersebut, tak jarang, masih ditemukan pada cara pandang dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan.
“Misalnya, masih ada stigma bahwasanya penyandang disabilitas intelektual ataupun mental tidak memiliki kapabilitas untuk bisa menyampaikan apa yang secara praktik mereka hadapi dan alami. Pertanyaan dari Hakim terindikasi melanggengkan stigma di masyarakat dan berujung kekerasan verbal pada penyandang disabilitas,” kata Kyntan.
Urgensi Kuat
Sementara itu, Peneliti PUKAT UGM Yuris Rezha Kurniawan mengatakan, urgensi atas inisiasi Raperma Disabilitas kian kuat dengan adanya berbagai regulasi terkait perlindungan hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Indonesia. Regulasi-regulasi ini pun dipertimbangkan sebagai landasan yuridis dalam Naskah Akdemik Raperma Disabilitas.
Salah satu regulasi yang dimaksud misalnya adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). “UNCRPD mengatur soal pengakuan hak-hak disabilitas, termasuk hak yang jauh lebih luas daripada Undang-undang Penyandang Cacat, termasuk juga soal kewajiban negara untuk memperhatikan dan melindunginya,” jelas Yuris.
Yuris lantas menyorot Pasal 3 dan Pasal 15 dari konvensi internasional tersebut, yang mengatur perihal hak penyandang disabilitas atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum dan akses terhadap peradilan. “Pasal 5 dan pasal 13 ini mengamanatkan apa yang nanti akan disusun dalam Perma ini,” tuturnya.
Aturan ini pun telah diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Ada di Pasal 9, mengenai hak kesetaraan di dalam hukum, diakui bisa mewakili dan mewarisi harta, masalah keuangan perbankkan dan sebagainya. Termasuk juga yang di-highlight adalah Pasal 28 dan 29 tentang bantuan hukum, pasal 30 tentang penilaian personal, Pasal 31 sampai 38 tentang penyesuaian dalam proses peradilan penyandang disabilitas, dan pasal 36 tentang kewajiban institusi badan hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak,” papar Yuris.
Selain itu, Yuris juga menyorot Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 yang menurutnya telah memperluas mandat penyediaan akomodasi yang layak di pengadilan. “Khususnya Pasal 12, yang sebenarnya sudah spesifik memandatkan lembaga penegak hukum untuk menyusun standar pemeriksaan penyandang disabilitas, meliputi kualifikasi penyidik, hakim, atau petugas masyarakat sesuai kewenangannya, termasuk fasilitas bangunan, akses layanan, serta prosedur pemeriksaan,” jelasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bagian dari proses advokasi SAPDA bersama PUKAT UGM dalam menginisiasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Advokasi ini berlangsung dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Seperti diketahui, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama, dan Militer-Tata Usaha Negara, telah menerbitkan SK tentang penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Kendati begitu, ketiga aturan internal tersebut masih berfokus kepada pemberian sarana prasarana di meja PTSP. Karena itu, Peraturan Mahkamah Agung dibutuhkan untuk mengisi sejumlah kekosongan hukum, utamanya soal standar pemeriksaan oleh Hakim.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)