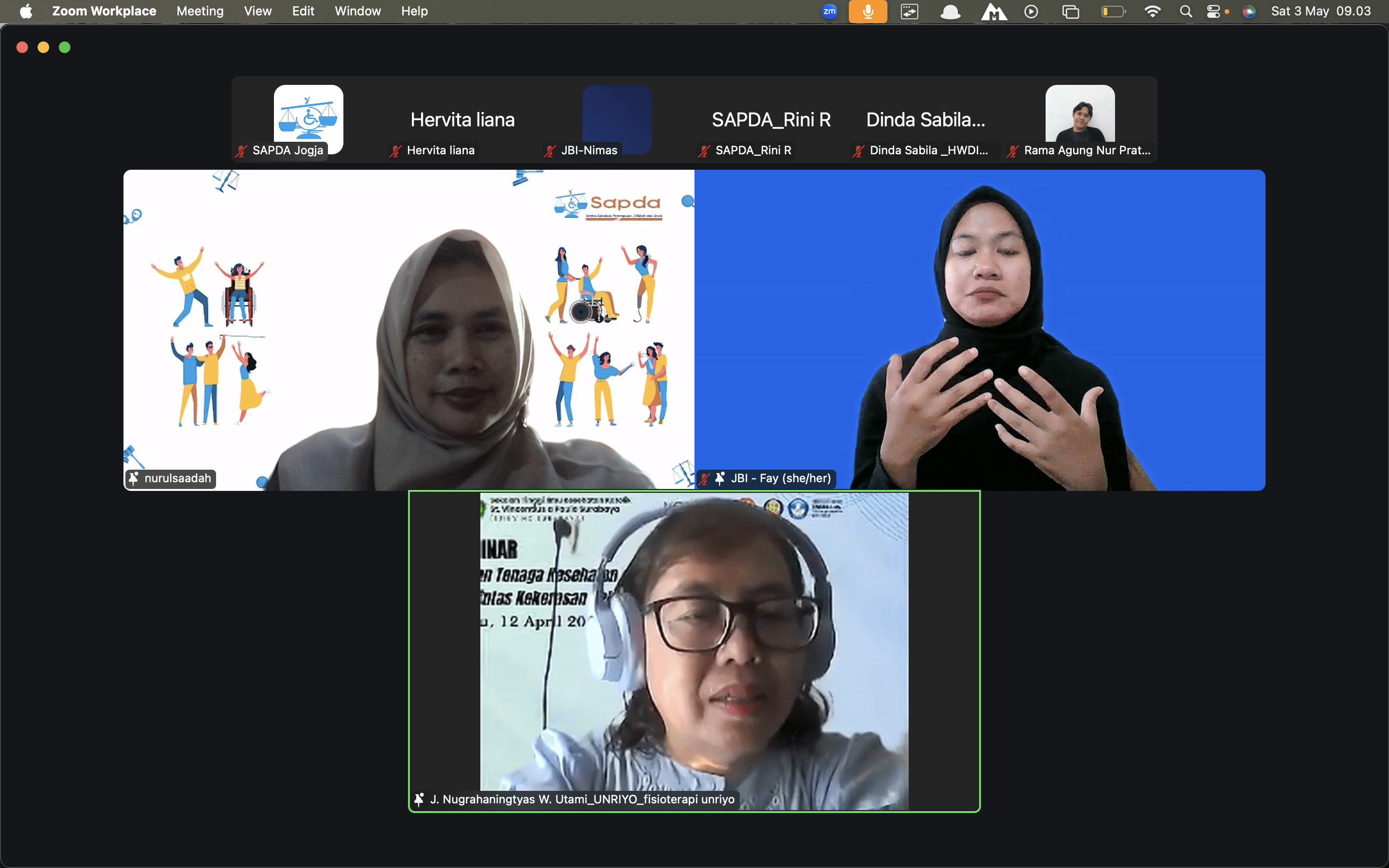Penyandang disabilitas masih mengalami beragam hambatan dalam mengakses layanan pengadilan. Standar pemeriksaan yang inklusif berbasis pemenuhan akomodasi yang layak sangat penting agar penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum terlindungi dan terpenuhi hak-haknya dalam proses peradilan.
Berbagai perwakilan organisasi penyandang disabilitas menyampaikan pengalamannya masing-masing berhadapan dengan hukum dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Mengenai Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang diselenggarakan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Rabu (5/7).
Salah satu hambatan yang diceritakan adalah minimnya perspektif disabilitas dalam pelayanan yang diberikan aparatur pengadilan. Salah satu peserta, Sri Lestari, mengatakan belum semua petugas pengadilan memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. “Waktu itu enggak ada (yang membantu mendorong kursi roda). Saya (bermobilitas) sendiri. Didorong cuman waktu mau naik, oleh satpam,” kata Sri yang menyandang disabilitas paraplegia.
Sri juga merasa kesulitan mengakses layanan pengadilan karena sarana-prasarana yang belum sepenuhnya aksesibel. “Saya ketika naik itu masih harus dibantu. Di dalam ruangan juga, untuk pakai kursi roda agak (mengalami) keterbatasan karena sempit. Di ruang mediasi pun juga agak sempit untuk kursi roda. Di kamar mandi, itu untuk belok sangat sulit,” katanya.
Hambatan lain yang juga banyak diceritakan berkaitan dengan komunikasi. Cerita ini salah satunya dibagikan oleh Anes dari Komite Disabilitas DIY saat menjadi saksi ahli dalam persidangan penyandang disabilitas Tuli pelaku tindak pidana. Saat itu, Anes mengalami hambatan komunikasi karena pelaku hanya memahami bahasa isyarat ibu. Sementara JBI yang memahami bahasa komunikasi pelaku justru tidak dihadirkan.
“Dengan Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia) (pelaku) enggak menangkap, apalagi SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia). Itulah yang menghambat sidang. Bercampur-campur dan enggak jelas. Karena muter-muter, hakimnya juga bingung sidangnya itu mengarahkan tentang apa,” ujar Anes.
Pengalaman hampir serupa juga dijumpai oleh Suwarni saat mendampingi penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan. Korban mengalami hambatan komunikasi karena hanya memahami bahasa isyarat ibu. Namun, Suwarni dan orang tua korban yang memiliki kapasitas menjembatani komunikasi korban justru dilarang untuk masuk persidangan. “Saya tidak diajak. Bahkan tidak dikabari. Makanya ketika pulang dia (korban) langsung cerita ke saya ditanyai banyak hal,” tuturnya.
Larangan perlibatan pendamping secara langsung di persidangan juga dialami oleh Dwi dari Gerkatin Sleman. Dwi yang saat itu menjadi JBI Tuli memiliki peran penting untuk menjembatani komunikasi korban dengan aparat penegak hukum. Alih-alih melibatkan Dwi, proses pemeriksaan justru dilakukan hanya melibatkan JBI Dengar. Sementara Dwi hanya dilibatkan dalam penulisan kronologi kasus secara jarak jauh.
“Saya menjelaskan, pendamping harus dari awal kasus. Tetapi kenapa malah tidak dihadirkan juga ketika berproses langsung? Saya kan enggak bisa maksimal membantu kalau mengerjakan dari rumah. Saya memberikan masukan itu ke pengadilan dan PPA, kalau pendamping itu harusnya datang, tidak hanya mengerjakan dari rumah,” tegasnya.
Di sisi lain, ketiadaan penilaian personal turut memberikan hambatan tersendiri. Erna dari komunitas disabilitas paraplegia mengutarakan ia belum pernah melalui proses penilaian personal selama mengakses di pengadilan. Alih-alih dilakukan penilaian personal, Erna justru diwajibkan memberikan surat keterangan disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter. “Surat itu menyatakan bahwa saya adalah difabel. Cuma itu saja. Katanya surat itu fungsinya kalau suatu saat saya tidak bisa hadir di persidangan, surat itu bisa digunakan,” ceritanya.
Tak hanya soal minimnya aksesibilitas dan perspektif disabilitas, hambatan juga hadir dalam bentuk kekerasan berulang yang terjadi di dalam persidangan. Salah satu peserta dari Gerkatin DIY menceritakan bagaimana ia justru menjadi korban kekerasan seksual saat mendampingi penyandang disabilitas Tuli berhadapan dengan hukum perdata perceraian.
“Hakim malah menanyakan perihal hal-hal pribadi pada saya, bukan kepada yang berperkara. Misalnya ‘Kamu kok cantik, sudah menikah belum? Kok kamu tahu apa itu hubungan seksual? Oh isyarat hubungan seksual itu seperti itu ya’. Terus dipraktikkan sama hakimnya dan mengikuti isyarat hubungan seksual, dan hakimnya ketawa-ketawa,” tuturnya.
Berbagai cerita mengenai hambatan dan tantangan penyandang disabilitas yang telah dihimpun akan menjadi bahan masukan untuk mendukung fakta empirik pada Draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang saat ini tengah disusun oleh SAPDA bersama Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM).
Yuris, salah satu peneliti dari PUKAT UGM yang berkontribusi dalam penulisan Draft Naskah Akademik Raperma Disabilitas mengatakan Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan dibawahnya perlu didorong untuk bisa memberikan akomodasi yang layak untuk teman-teman penyandang disabilitas.
“Secara empiris, banyak kasus yang terbengkalai, banyak kasus terdiskriminasi, banyak kasus dimana teman-teman disabilitas tidak bisa mendapatkan proses peradilan yang adil. Secara hukum dan kebijakan kita itu enggak kurang-kurang. Negara memiliki kewajiban memberikan akomodasi kepada teman-teman disabilitas dalam konteks hukum dan peradilan,” pungkas Yuris.
Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan pendanaan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)