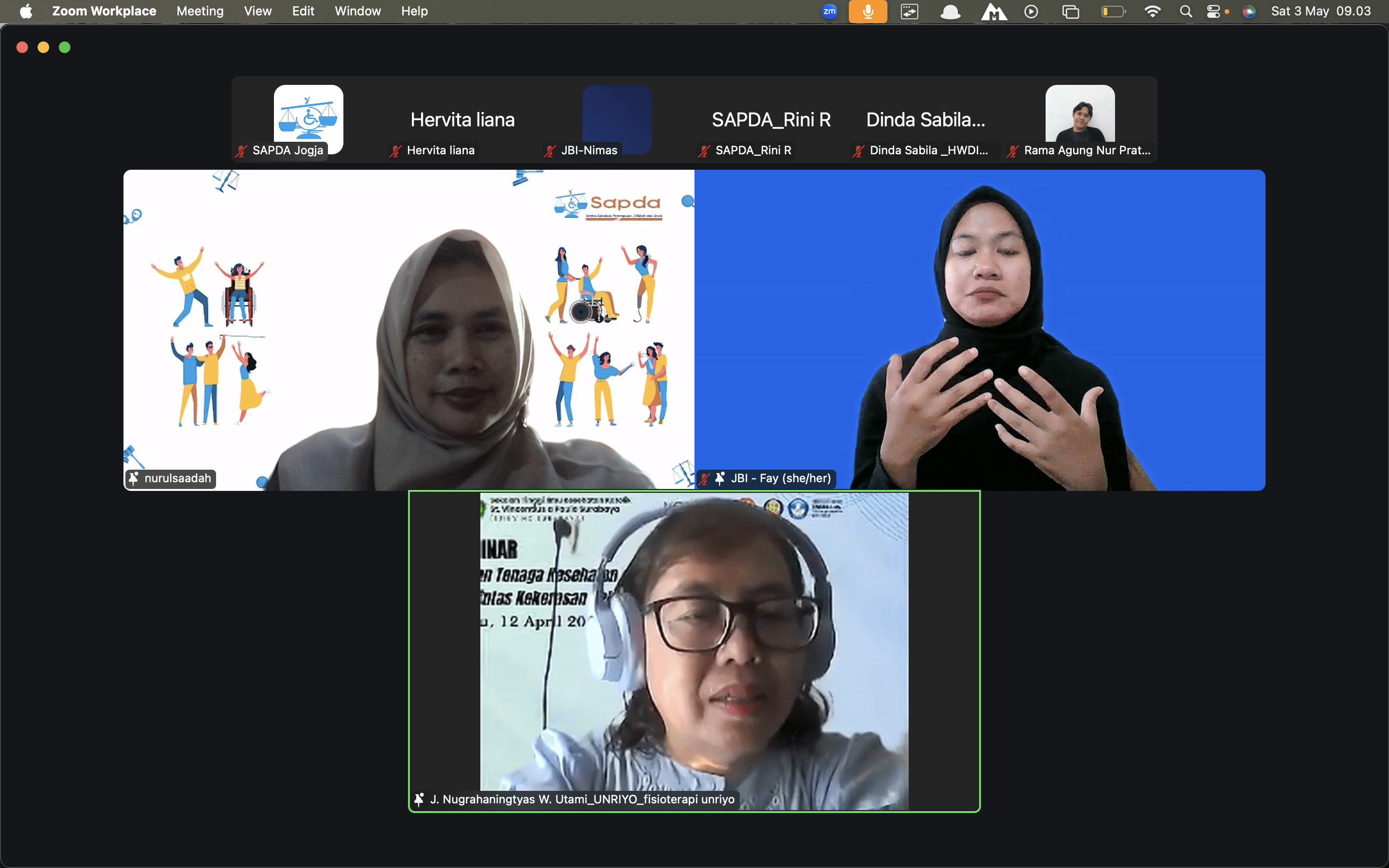Pembuatan dan implementasi kebijakan di Indonesia selama ini sekedar berfokus pada pemberian layanan yang setara, namun belum mempertimbangkan aspek-aspek gender dan disability. Inilah yang menyebabkan perempuan dan penyandang disabilitas tidak memperoleh keadilan sesuai dengan porsinya.
Hal tersebut merupakan poin utama dari paparan Direkur SAPDA Nurul Saadah dalam Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Regulasi di Indonesia dalam Perspektif GEDSI yang diselenggarakan SAPDA pada Rabu, (21/10) lalu.
“Keadilan itu sendiri seringkali tidak melihat itu dari kacamata perempuan disabilitas. Ada persoalan-persoalan yang mendasar pada perempuan disabilitas. Dan itu tidak diungkap di sana (kebijakan di Indonesia),” katanya.
Karena itulah, diperlukan perspektif baru yang kiranya dapat memperbarui praktik inklusi sosial di Indonesia. Perspektif baru yang dimaksud yakni: konsep inklusi sosial berperspektif gender dan disabilitas.
Menurut Nurul, konsep tersebut juga diperuntukan sebagai budaya tanding atas konsep inklusi sosial umum yang sudah ada. “Karena inklusi sosial (umum) itu juga seringkali masih belum mempertimbangkan kebutuhan dan persoalan khusus bagi perempuan dan perempuan disabilitas,” jelasnya.
Nurul berharap, konsep inklusi sosial berperspektif gender dan disabilitas ini bisa menjadi alat baru untuk meneropong isu ketidakadilan perempuan disabilitas di Indonesia. Sebab, alat lama yang telah banyak digunakan, sebut saja seperti gender analysis pathway, hanya mempertimbangkan peran sosial perempuan disabilitas di ranah publik.
Padahal, menurut Nurul, peran sosial di ranah domestik juga tidak kalah pentingnya. “Bagaimana ruang domestik kemudian memastikan bisa memberikan dukungan adil bagi perempuan dengan disabilitas. Dia bisa mendapatkan manfaat, bisa berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, kemudian bisa mendapatkan manfaat atas hak propertinya, kemudian juga bisa mengontrol atas semuanya,” katanya.
Selain itu, konsep ini juga menjadi alternatif dari konsep feminisme mainstream. Dalam paparannya, Nurul kemudian memperkenalkan konsep feminisme disabilitas yang ditemukan Rose Mary. Rose sendiri memandang bahwa perempuan disabilitas memiliki pengalaman ketertindasan yang berbeda ketimbang perempuan lainnya.
Misalnya saja, terkait akar ketertindasan. Bagi perempuan disabilitas, akar ketertindasan bukan hanya berasal dari tubuh, melainkan juga relasi kuasa di hadapan laki-laki. “Bagaimana dia (laki-laki) menghargai perempuan sebagai seorang disabilitas? Dia cantik? Tidak cantik? Layak atau tidak? Dijadikan istri atau tidak? Dan sebagainya,” kata Nurul.
Baca juga: Mainstreaming Gedsi dan Riset untuk Remaja Disabilitas dan Tanpa Disabilitas
Senada dengan Nurul, peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Sri Wiyanti Eddyono juga menegaskan bahwa setiap perempuan disabilitas memiliki keragaman situasi dan masalah. “Di Jakarta, perempuan disabilitas mendapatkan fasilitas. Tapi di Karawang malah dihukum pancung karena ada diskriminasi berlapis yang dialami perempuan itu,” katanya.
Menurut Sri, keragaman tersebut lah yang harus dipahami oleh aparat pembentuk kebijakan serta seluruh pemangku kepentingan yang ada. “Karena seringkali banyak upaya untuk menghomogenisasi atau membuat seolah-olah problema perempuan disabilitas itu hanya satu jenis. Padahal tidak demikian,” jelasnya.
Menurutnya, penelitian tentang perempuan dan disabilitas yang baik harus berbasis pengalaman dan dengan mengacu pada prinsip penguatan hak dan implementasinya. “Tujuan penelitian tidak semata-mata untuk mendapatkan pengetahuan baru, tapi juga untuk melihat gap-gap apa atau persoalan apa yang muncul dalam isu perempuan disabilitas,” katanya.
Selain itu, peneliti juga harus memperhatikan etika penelitian. Dalam konteks isu disabilitas, kewajiban tersebut salah satunya dapat diwujudkan dengan memperhatikan keselamatan penyandang disabilitas yang menjadi subjek penelitian, di samping keselamatan peneliti itu sendiri.
“Resiko keselamatan peneliti dalam melakukan penelitian dan keselamatan partisipan penelitian kita supaya mereka tidak mendapatkan harm atau kesulitan ketika mereka melakukan penelitian dengan kita atau pasca penelitian kita,” terangnya.
Terakhir, peneliti harus menempatkan diri dalam posisi yang setara dengan subjek penelitian. Dengan kata lain, peneliti dan subjek penelitian harus sama-sama diuntungkan oleh sebuah penelitian. “Sejauh mana penelitian dapat memberi manfaat kepada pihak lain sehingga penelitian tidak semata-mata untuk kepentingan peneliti,” jelasnya.
Dalam paparannya, Sri juga menyayangkan menurunnya jumlah penelitian bertema perempuan di dan disabilitas di Indonesia. Berdasarkan temuannya, ia menjelaskan bahwa hingga 20 Oktober 2020 terdapat 7.770 penelitian dengan tema tersebut di mesin pencari Google Scholar.
Jumlah penelitian terbanyak terdapat pada tahun 2016, yakni 6.290 penelitian. Angka itu menurun pada tahun 2019 menjadi 3.100 penelitian, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 1.110 penelitian.
Konferensi Nasional Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Regulasi di Indonesia dalam Perspektif GEDSI merupakan bagian dari program Riset Advokasi Perempuan Disabilitas Berbasis Gender, Disability and Social Inclusion (GEDSI) yang telah berjalan sejak 8 Oktober 2019 lalu.
Konferensi ini juga menandai peluncuran hasil penelitian dari 17 orang periset yang dibukukan dalam bentuk tulisan populer. Dalam konferensi hadir pula sebagai pembicara: Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani Rontisulu, anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM PBB) dari Convention for Rights of People with Disability (CRPD) Risnawati Utami, dan Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan terhadap Perempuan Andy Yentriyani.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)