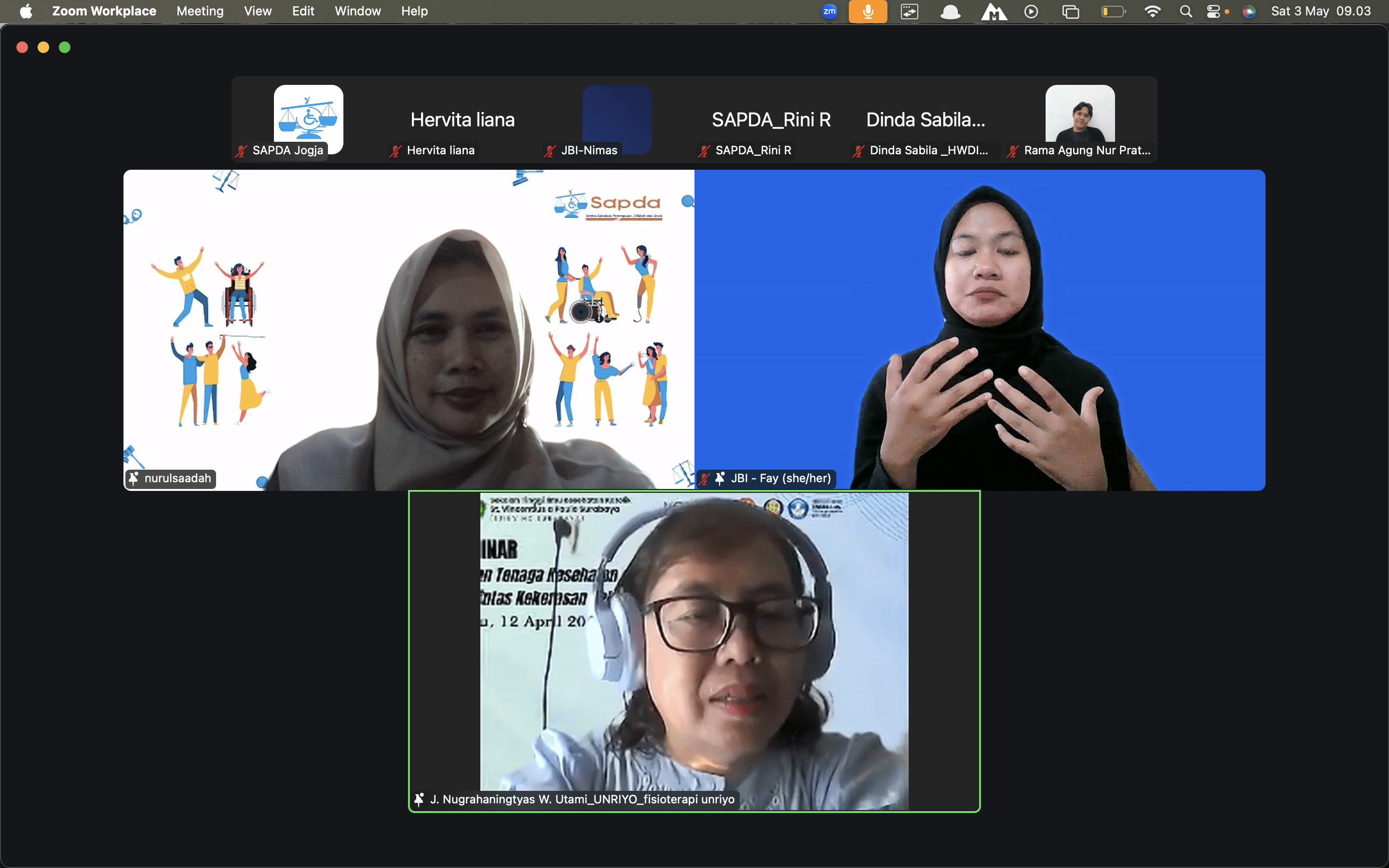Pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas kekerasan menyimpan beragam cerita di baliknya. Berbagai tantangan dihadapi lembaga penyedia layanan dalam memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh keadilan, mulai dari kendala komunikasi, layanan yang belum didesain untuk memenuhi kebutuhan disabilitas, hingga penolakan dari keluarga atau bahkan korban itu sendiri.
Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) telah menghimpun pengalaman berbagai lembaga penyedia layanan di berbagai daerah di Indonesia dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan. Cerita-cerita tersebut dibagikan di dalam lokakarya Penyusunan, Penulisan dan Publikasi Catatan Tahunan tahun 2022 pada (19/1).
Dari berbagai cerita yang disampaikan, kendala komunikasi diketahui menjadi salah satu tantangan terbesar terutama dalam pendampingan korban penyandang disabilitas Tuli. Kendala ini salah satunya disampaikan oleh Lafifa dari Lingkar Belajar untuk Perempuan (Libu Perempuan) Sulawesi Tengah. Latifa membagikan pengalaman betapa sulitnya mencari Juru Bahasa Isyarat di wilayah pendampingan kasusnya.
“Di Sulteng itu sangat minim sekali orang yang mengetahui bahasa isyarat. Jadi kami kesulitan mencari penerjemah. Ketika sudah saatnya kami mendampingi korban, juru bahasa isyaratnya malah berhalangan, ada kegiatan lain. Sehingga proses pendampingan kami menjadi terbatas. Pada saat juru bahasa isyaratnya itu berkenan untuk mendampingi, justru korban sudah pergi ke kota lain, ke Makassar,” kata Latifa.
Dorkas, dari Yayasan Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (YAPHI) juga menyampaikan pengalaman yang tidak jauh berbeda. Ketika melakukan pendampingan kepada korban anak penyandang disabilitas Tuli, pihaknya melibatkan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai penerjemah bahasa isyarat. Namun, dalam proses penggalian keterangan, ternyata guru tersebut turut mengalami keterbatasan bahasa.
“Itu nampak sekali di awal ketika kami melakukan investigasi. Kami menghadirkan guru SLB yang harapannya dapat menjembatani kami berkomunikasi dengan anak. Tetapi faktanya guru SLB ini pun juga mengalami hambatan komunikasi, karena si anak ini menggunakan bahasa isyarat campuran: SIBI, BISINDO dan gestur. Sedangkan guru SLB ini hanya memahami bahasa isyarat SIBI,” tutur Dorkas.
Lebih dari itu, Dorkas juga merasakan kesulitan dalam mencari relawan Juru Bahasa Isyarat yang bersedia membantu pendampingan dari awal pemeriksaan sampai dengan proses peradilan. Hal ini biasanya merupakan permintaan dari aparat penegak hukum untuk menjaga konsistensi keterangan. “JBI tidak boleh berubah-ubah. Sementara teman-teman JBI ini kan juga memiliki pekerjaan di lain tempat,” tambahnya.
Belum lagi ketika aparat penegak hukum meminta juru bahasa isyarat harus bersertifikat, seperti yang dialami Puput dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kendati Juru Bahasa Isyarat sebenarnya tidak wajib bersertifikat, namun terkadang masih ada aparat penegak hukum yang mewajibkan kualifikasi tersebut. Padahal juru bahasa isyarat juga dapat berasal dari orang terdekat yang memahami bahasa komunikasi korban dan dipercaya oleh korban.
“Saat berkoordinasi dengan kepolisian, penyidik meminta supaya kami menghadirkan juru bahasa isyarat. Kami sempat mendapatkannya dari satu komunitas yang mengajarkan bahasa isyarat. Jadi kami coba hadirkan dan kami hubungan dengan teman penyidik. Tapi saat berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, ternyata jaksanya tidak mau karena juru bahasa isyarat yang kami libatkan belum punya sertifikasi resmi,” katanya.
Tak hanya korban penyandang disabilitas Tuli, kendala komunikasi juga sering kali terjadi di dalam pendampingan terhadap korban penyandang disabilitas Mental dan Intelektual. Seperti cerita yang disampaikan Ismail dari Suara Perempuan Sulawesi Utara misalnya, ketika mendampingi anak penyandang disabilitas Mental Kejiwaan, pihaknya sulit menggali informasi secara konsisten. “Kadang-kadang informasinya berbeda-beda. Hari ini sampaikannya lain, besoknya lain,” ujarnya.
Kiki, dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung juga menyampaikan tantangan serupa. Ia bercerita, ketika mendampingi penyandang disabilitas Intelektual korban kekerasan, korban sulit menyampaikan keterangan karena hambatan kedisabilitasannya yang juga diperburuk dengan trauma mendalam. Situasi ini akhirnya menghambat proses penyelidikan, sehingga kasus harus berhenti dalam waktu yang cukup lama.
“Saat beberapa kali dilakukan pemeriksaan, korban tidak mau untuk berbicara. Tetapi ketika membicarakan hal-hal di luar kejadian itu dia mau merespon. Kalau sudah mengarah pada peristiwa ini, dia tidak mau merespon sama sekali. Akhirnya kasusnya sendiri sempat mandeg satu tahun lebih. Pihak kepolisian menekankan bahwa korban harus bicara, memberikan keterangan dan mengatakan bahwa ia mengalami kekerasan seksual,” tutur Kiki.
Minimnya Layanan Ramah Disabilitas
Di samping kendala komunikasi, tantangan dalam pendampingan kasus korban kekerasan tak jarang juga disebabkan karena layanan yang belum memadai. Kiki dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung menceritakan kesulitannya saat mencari layanan pemulihan trauma korban pada Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Layanan tersebut tidak bisa didapatkan kendati UPTD PPA di wilayah pendampingannya sudah memiliki MoU dengan rumah sakit jiwa.
“Ternyata tidak bisa karena mereka ber-MOU dengan rumah sakit jiwa untuk proses pemeriksaan atau visum. Untuk pemulihan korban enggak bisa. Karena korban ini mengalami disabilitas bukan karena dampak kekerasan yang dialami. Jadi mereka tidak bisa mengakomodir atau membantu memberikan layanan untuk pemulihan jika itu adalah penyakit penyerta, bukan akibat dari kekerasan,” tutur Kiki.
Situasi yang kurang lebih sama juga ditemui Kiki ketika hendak mengakses layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas Intelektual korban kekerasan di rumah aman milik pemerintah. Ia baru menemukan bahwa pemerintah daerah di wilayah pendampingannya sama sekali belum menyediakan layanan seperti itu. Akhirnya, Kiki pun harus bergantung pada panti rehabilitas milik swasta.
“Meskipun saat ini korban sudah berada di panti rehabilitasi milik swasta, tetapi kita mengakses panti ini juga enggak mudah. Kita harus koordinasi dahulu dengan Dinas Sosial. Itu pun awalnya juga ditolak karena korban masih berurusan dengan proses hukum,” kata Kiki.
Ketidaksiapan lembaga dalam memenuhi hak penyandang disabilitas juga pernah dijumpai oleh Dorkas dari YAPHI. Saat mendampingi anak penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan seksual, ia mendapati bahwa kepolisian merasa kesulitan menggali keterangan karena anak tidak memahami istilah-istilah berkaitan seksualitas dan reproduksi. Kepolisian tidak memiliki alat peraga apapun yang dapat membantu proses pemeriksaan.
“Kami yang berupaya untuk mencari manekin, bertadine, hand body agar bagaimana si anak bisa memahami pertanyaan yang diminta oleh kepolisian. Jadi memang ketidaksiapan fasilitas ini menjadi kendala juga. Dan itu mengakibatkan banyak sekali keterangan yang miss antara yang dimaksud korban dengan apa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian,” ujar Dorkas.
Dorkas juga bercerita layanan-layanan yang tersedia di wilayah pendampingannya belum terintegrasi satu sama lain, baik dari lembaga penyedia layanan maupun aparat penegak hukum. “Kami selalu menyampaikan kendala-kendala yang kami hadapi dan itu coba kami advokasi. Tetapi advokasi itu harus berhenti pada satu lembaga, misalnya kepolisian. Selesai di sana, kami harus advokasi lagi di kejaksaan. Nanti masih harus advokasi lagi di pengadilan,” tutur Dorkas.
Keluarga dan Korban Turut Menghambat
Hambatan pendampingan penyandang disabilitas korban kekerasan tidak jarang bukan hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga kondisi internal seperti minimnya dukungan dari lingkungan sekitar korban, atau bahkan datang dari korban itu sendiri. Rosmiyati dari LBH APIK Sulawesi Selatan misalnya, ia becerita pernah mendapati kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas Mental Kejiwaan tidak pernah tertangani karena keluarga korban enggan untuk melapor.
“Sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan ke teman-teman pendamping dan paralegal yang ada di sekitar wilayah korban supaya tetap dilaporkan. Hanya saja dari pihak korban sudah tidak mempedulikan itu. Sekarang korban tetap keluar-keluar ke warung, ke puskesmas, tiduran di pinggir jalan. Harus diantisipasi jangan sampai terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” jelas Rosmiyati.
Ismail dari Suara Perempuan Sulawesi Utara turut menyampaikan pengalamannya ketika merasakan kesulitan dalam mendampingi penyandang disabilitas korban kekerasan, lantaran keluarga memiliki penerimaan yang kurang baik ditambah berada di bawah garis kemiskinan. “Sampai sekarang kasusnya tertunda karena pelaku adalah keluarga dekat dari korban,” katanya.
Dorkas dari YAPHI juga membagikan pengalaman serupa. Ketika ia mendampingi anak penyandang disabilitas Tuli korban kekerasan, keluarganya sendiri juga mengalami keterbatasan komunikasi karena tidak memahami bahasa korban, sehingga tidak mampu menggantikan peran penerjemah. Di waktu lain, Dorkas juga mendapati keluarga yang cenderung membiarkan anaknya mengalami kekerasan berulang.
“Misal ada anak yang berumur 15 tahun, orang tuanya bilang ‘ya sudahlah, terlanjur begini, dinikahin saja’ dan lain sebagainya. Pemahaman seperti masih ada di orang tua. Membangun pemahaman di pihak keluarga menjadi tantangan tersendiri yang kami hadapi. Cara ini perlu dilakukan perlahan-lahan terlebih ketika banyak orang tua dengan anak disabilitas yang mudah merasa pesimis,” tandas Dorkas.
Situasi-situasi serupa sering kali bahkan tidak datang dari keluarga, melainkan korban itu sendiri. Ismail dari Suara Perempuan Sulawesi Utara bercerita, kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap penyandang disabilitas Netra yang didampinginya harus berhenti dalam waktu yang cukup lama karena korban enggan untuk melapor. “Ibu ini memberikan informasi karena masih sayang sama suaminya meskipun sudah dilakukan kekerasan,” katanya.
Kiki Ayu dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung turut membagikan pengalamannya ketika mendampingi penyandang disabilitas Mental Kejiwaan korban kekerasan. Ia mengaku merasa kesulitan karena korban sulit ditemui dan sering berpindah-pindah tempat. “Dia tidak stand by ada di ruma, aktifitasnya selalu di lua. Sehingga kita tidak mengetahui dengan pasti korbannya ini ada di mana. Korban harus ada dulu baru bisa dibuatkan laporan,” tuturnya.
Sebagai informasi, lokakarya Penyusunan, Penulisan dan Publikasi Catatan Tahunan 2022 diselenggarakan diselenggarakan sebagai momen untuk berbagi pengalaman pembuatan Catahu Penaganan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas. Pada periode sebelumnya SAPDA telah membuat Catahu serupa dengan hanya menghimpun data dari kasus-kasus yang diterima RCB SAPDA. Sedangkan pencatatan tahun ini tidak lagi dilakukan secara mandiri oleh SAPDA, tetapi akan melibatkan berbagai lembaga penyedia layanan di berbagai daerah di Indonesia.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencatat pengalaman lembaga penyedia layanan dalam penanganan kasus dengan korban penyandang disabilitas; sekaligus melakukan konsolidasi pendokumentasian kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas. Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)