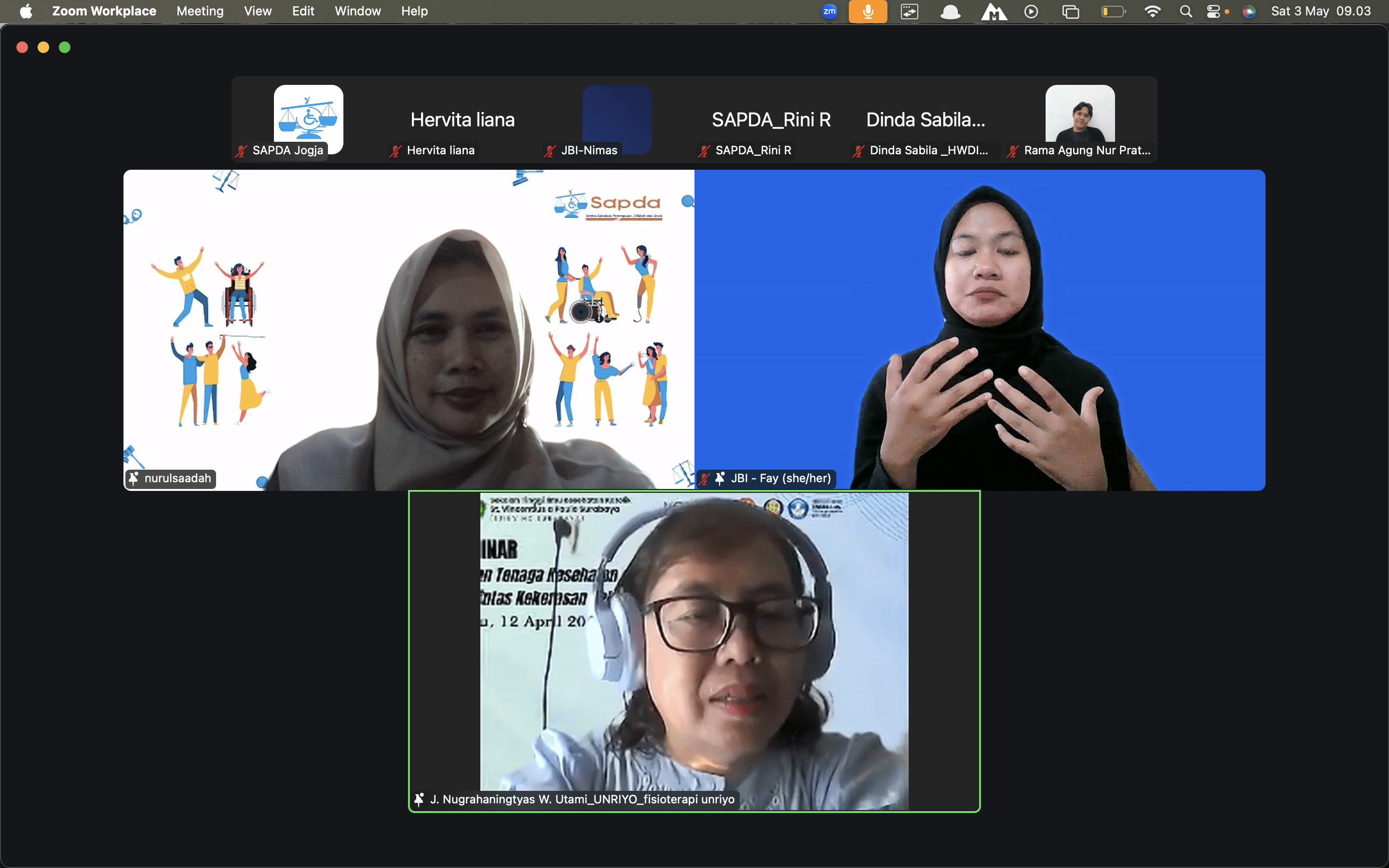Penyelesaian perkara anak dan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, lembaga peradilan harus menyediakan layanan akomodasi khusus berkaitan dengan pemulihan psikis para korban.
Akomodasi yang dimaksud bisa dipenuhi dengan mengajukan permintaan terhadap tenaga kesehatan seperti psikolog atau psikiater yang bisa memberikan penilaian terhadap kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas. Di sinilah kualitas sistem rujukan sangat berperan.
Sekretarus Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial Kanya Eka Santi menjelaskan bahwa untuk menciptakan sistem rujukan yang efektif bagi para penyandang disabilitas, lembaga peradilan setidaknya harus lebih dahulu memahami ragam disabilitas.
“Pemahaman kita terhadap jenis disabilitas akan berkonsekuensi pada jenis-jenis bantuan terutama anak atau berhadapan dengan hukum,” katanya Kanya ketika menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Mekanisme Sistem Rujukan untuk Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum pada Rabu (11/11) lalu.
Menurut Kanya, rujukan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah secara referral langsung oleh pendamping penyandang disabilitas itu sendiri, dengan menghubungi kontak layanan khusus. Selain itu, rujukan juga diberikan antara pemberi layanan satu kepada pemberi layanan yang lain.
Namun, Kanya mengingatkan, di dalam sebuah proses rujukan, perujuk harus tetap melakukan pengawasan dan tidak mengambil sikap lepas tangan. “Agar klien atau siapa pun yang kita rujuk itu tetap termonitor, terjaga, terlindungi, keselamatan, dan hak-haknya,” tegas Kanya.
Terkhususkan untuk anak penyandang disabilitas, menurut Kanya, data-data yang akan dirujuk harus diperhatikan. Misalnya, data mengenai identitas detail anak seperti nama, tanggal lahir, anggota keluarga, dan alamat, serta identitas orang dewasa yang tinggal bersamanya.
“Kemudian sejarah yang relevan dengan anak dan rumah tangganya, apakah di dalamnya ada pelaku kekerasan. Juga informasi faktual tentang pengamatan, penilaian profesional terkait masalah anak, mengapa anak harus dirujuk, dan sebagainya. Itu menjadi data dasar yang harusnya ada dalam setiap mekanisme rujukan,” katanya.
Lebih lanjut, Kanya menjelaskan tiga komponen kunci dalam mekanisme rujukan. Pertama, perihal pemetaan layanan. Perujuk harus memperhatikan kemana ia membawa klien. “Bisa ke Lembaga Penyelenggara Sosial,kalau dia pelaku. Jika dia korban, bisa saja ditempatkan di rumah sosial,” jelasnya.
Kedua, instrumen rujukan yang dilibatkan juga harus terstandarisasi. Ketiga, juga harus ada kesepakatan formal antar penyedia layanan yang memberi dan menerima rujukan. “Karena harus ada berita acara serah terima rujukan,” kata Kanya.
Di samping itu, Amaliyah Mahsunah dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan bahwa sistem rujukan bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Indonesia belum cukup menjangkau ke tingkat daerah terpencil. “Setiap stakeholder sekecil apa pun harus saling mendukung dan bersinergi,” katanya.
Ia juga menyarankan agar negara memiliki tim terpadu yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan korban pasca proses peradilan. “Kemudian perlu dibentuknya peta alur sistem rujukan terhadap penanganan korban disabilitas seperti apa, sehingga juga kita bisa sama-sama memaksimalkan peran,” lanjut Amaliyah.
Senada dengan Amaliyah, Kepala Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Reza Faraby juga menegaskan perihal pentingnya tim terpadu tersebut.
“Dengan adanya tim terpadu yang memberikan perlindungan dan pemulihan korban, mungkin itu bisa menjadi salah satu cikal bakal untuk sinergitas stakeholder yang nantinya bisa menyusun bersama-sama peta alur rujukan,” kata Reza.
Diskriminasi Berlapis
Sistem rujukan, terutama yang terkait dengan pemulihan, tentunya juga sangat berguna bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Sebab, menurut Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Nurul Sa’dah, pengalaman kekerasan perempuan penyandang disabilitas sangat kompleks.
Kompleksitas di sini berarti bahwa mereka memiliki pengalaman diskriminasi yang berlapis, mulai dari di level keluarga, lingkungan, masyarakat, sampai negara. “Juga, perempuan dengan disabilitas mengalami kerentanan dari lahir sampai lansia, dalam seluruh proses perkembangan fisiknya, kehidupannya,” kata Nurul.
Ketika masih anak-anak, menurut Nurul, perempuan penyandang disabilitas banyak yang ditinggalkan dan tidak diperhatikan atau dipenuhi kebutuhannya oleh keluarga. “Bisa jadi karena orang tuanya tidak tahu, atau mereka memang tidak mempunyai pembiayaan untuk kemudian mendukung anak-anak disabilitas dengan kebutuhannya yang cukup banyak,” katanya.
Diskriminasi lantas berlanjut hingga ia remaja. Di sini mereka semakin rentan untuk menerima kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dalam Riset Siklus Kehidupan 2020 yang dilakukan SAPDA, ia menemukan bahwa perempuan penyandang disabilitas lebih mudah untuk keluar dari rumah dan berpisah dengan keluarganya saat mulai menginjak remaja.
“Itu merupakan bagian yang berkontribusi terhadap penciptaan kekerasan itu sendiri. Saat mereka di luar rumah, di luar keluarga, dukungan juga akan sangat berat, termasuk ketika mereka menumpang,” jelas Nurul.
Di tahap kehidupan selanjutnya, yaitu menikah, perempuan penyandang disabilitas berpotensi mengalami kekerasan dari pasangannya. Mereka juga bisa mengalami hambatan saat hendak mengambil keputusan sendiri perihal mengandung dan melahirkan anak.
“Saat mereka tidak diperbolehkan untuk hamil, maka mereka akan dikontrasepsi, atau kemudian setelah itu ada aborsi. Bahkan setelah punya anak tidak diperbolehkan untuk mengasuh anaknya sendiri dan dipisahkan dari anaknya, tutur Nurul.
Selain itu, mereka juga bisa dimanfaatkan secara ekonomi dan fisik, mengingat posisi tawarnya yang rendah dihadapan orang lain. “Rendah karena dianggap tidak dapat memenuhi standar kecantikan dan menjalankan peran sosial secara optimal,” kata Nurul.
Kemudian, saat memasuki dewasa akhir, perempuan penyandang disabilitas juga harus menanggung beban ganda. Mereka harus menghidupi keluarga dan anak sekaligus mempertahnkan keluarga secara sosial-normatif di saat yang sama. “Namun mereka tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, pasangan, dan lingkungan sosialnya,” jelas Nurul.
Kondisi kian diperburuk saat perempuan disabilitas enggan melapor. Selain layanan peradilan yang tidak aksesibel, faktor utama lain keraguan mereka adalah tidak adanya informasi yang terjangkau. “Kalau mereka sudah memiliki teman sebaya atau konselor sebaya, setidaknya mereka bisa melaporkan, berbagi, dan mendapatkan informasi,” kata Nurul.
Ada pun faktor tambahan berkaitan dengan penguasaan aset. Dalam riset yang sama, Nurul menemukan bahwa sebagian besar aset, seperti tanah dan bangunan, milik perempuan penyandang disabilitas dikelola dan diatasnamakan anggota keluarga lainnya.
Maka, ketika hendak melapor, ada ketakutan dari diri mereka bahwa aset-aset tersebut mungkin akan hilang. “Jadi itu sebenarnya persoalan-persoalan yang sangat internal bagi perempuan disabilitas yang sangat menghambat dalam proses penanganan atau penyelesaian perkara,” ujar Nurul.
Diskusi yang dimoderatori oleh Astriyani dari Justice Reform Advisor (AIPJ 2) ini merupakan bagian dari perhelatan Temu Inklusi 2020, yakni program dua tahunan yang pertama kali dirintis oleh SIGAB pada Desember 2014 lalu. Temu Inklusi merupakan wadah terbuka yang mempertemukan berbagai pihak pegiat inklusi difabel.
Menurut Astri, diskusi ini sangat penting untuk membangun sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan sistem rujukan peradilan yang efektif bagi penyandang disabilitas Indonesia. “Sebab saya melihat bahwa isunya sangat crosscutting di antara pemangku kebijakan yang terlalu tersebar di banyak Kementerian dan lembaga,” katanya.
Turut hadir pula dalam diskusi yakni: penanggungjawab Temu Inklusi sekaligus direktur Sigab Indonesia Suharto, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol Ema Rahmawati, dan Astri Kusuma Mayasari dari Direktorat Pertahanan.
Selain itu, juga Keamanan Bappenas, serta Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki, serta Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nyimas Aliah.
Diskusi juga diisi dengan testimoni sejumlah perwakilan kelompok penyandang disabilitas, antara lain Siti Sa’dah dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Dwi Rahayu Februarti dari Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Sleman, serta Enik Hambarani dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)