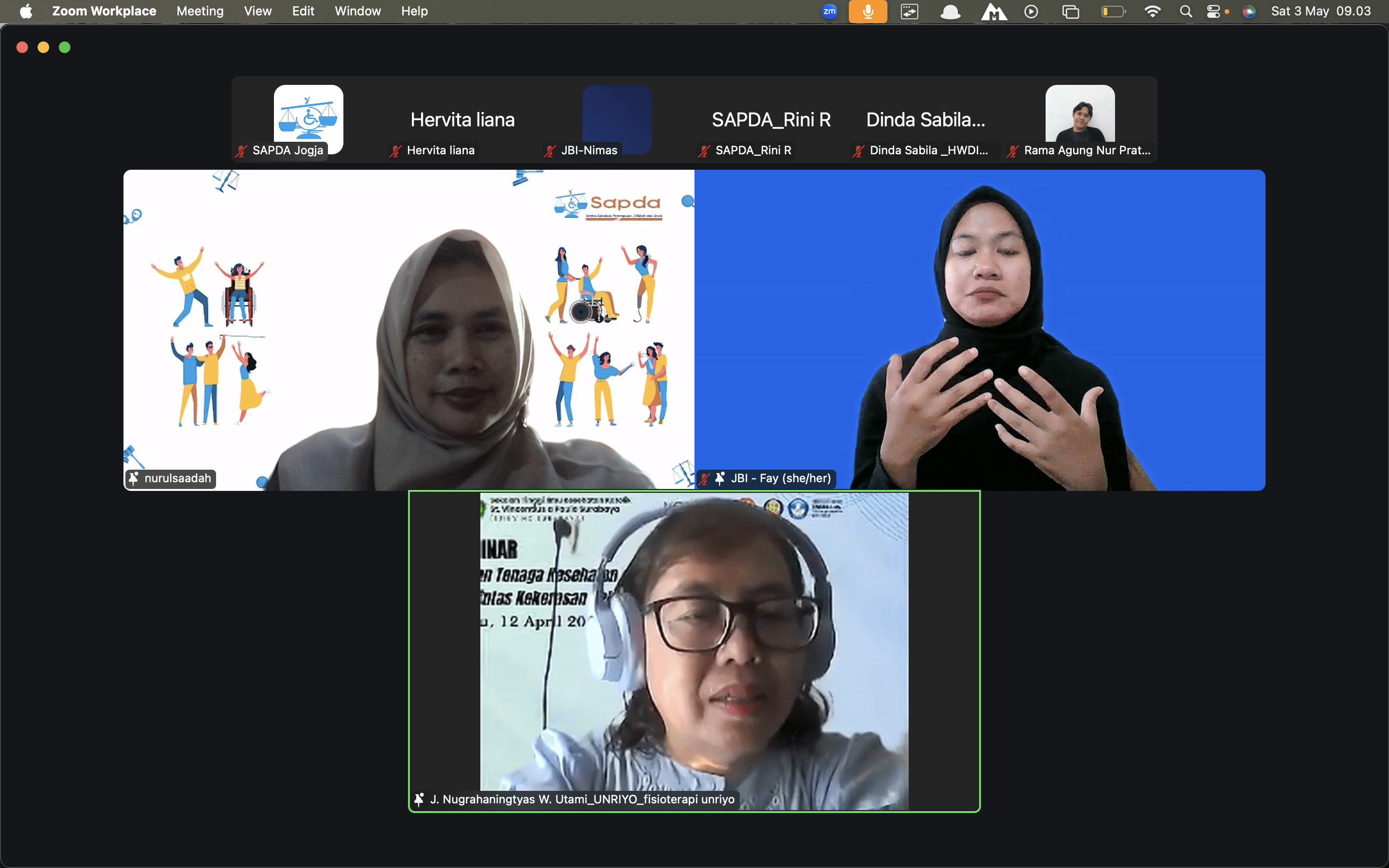Beban legalitas kemampuan Juru Bahasa Isyarat (JBI) menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendampingan penyandang disabilitas Tuli yang berhadapan dengan hukum. Teman-teman JBI Dengar maupun JBI Tuli misalnya, sering kali menerima penolakan hanya karena tidak memiliki sertifikat kemampuan bahasa isyarat. Akibatnya, pemenuhan hak atas akomodasi yang layak bagi teman Tuli menjadi terhambat.
Arini, koordinator lembaga layanan penanganan kekerasan berbasis disabilitas Rumah Cakap Bermartabat (RCB) SAPDA mengatakan, kewajiban untuk memiliki sertifikat kemampuan bahasa isyarat bagi JBI cukup menjadi kendala dalam penanganan kasus. Sebab, setidaknya di Yogyakarta sendiri, belum tersedia layanan terkait sertifikasi kompetensi bahasa isyarat.
“Bahkan ada satu kasus yang berhenti satu tahun di tingkat penyidikan, enggak naik-naik, karena sulitnya untuk melibatkan dua orang JBI Dengar dan Tuli. Sampai sudah mentok karena memang tidak ada sertifikasi JBI,” kata Arini dalam diskusi kelompok terarah Sistem Rujukan Berbasis Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas, yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada akhir Mei lalu.
Menurut Nels, seorang JBI Dengar, selama ini penilaian kompetensi berbahasa isyarat seorang JBI diberikan secara langsung oleh penyandang disabilitas Tuli itu sendiri. Teman-teman dengar perlu terlebih dahulu menjalin interaksi dengan teman Tuli, memperbanyak aktivitas berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dengan mereka, sampai bisa mendapatkan kepercayaan sebagai JBI.
Langkah tersebut, menurut Nels, sekaligus merupakan bagian dari perjuangan agar bahasa isyarat mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari identitas budaya teman Tuli. “Jadinya kita selama ini selalu menggunakan pengakuan dari teman-teman Tuli, dasarnya adalah perspektif disabilitas. Walaupun tidak mendengar, mereka punya banyak cara untuk meng-crosscheck apakah seseorang bisa menjadi juru bahasa isyarat atau tidak,” ujarnya.
Irma dari Women Disability Crisis Center SAPDA menyarankan agar sertifikasi kemampuan bahasa isyarat bisa digantikan dengan surat keterangan dari organisasi disabilitas atau lembaga layanan yang menugaskan JBI. “Itu bisa menjadi masukan yang menarik juga, karena di wilayah-wilayah lain belum tentu ada yang seperti di Jogja,” pungkasnya.
Namun, Nels mengingatkan, bahwa organisasi disabilitas yang merekomendasikan penugasan JBI harus dipastikan memiliki perspektif disabilitas. Sebab tidak jarang masih ada organisasi disabilitas yang kurang memperhatikan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas Tuli dalam menyediakan JBI, sehingga justru berujung pada pengalaman diskriminasi.
“Misalnya, ketika ada kegiatan, mengundang JBI dari guru SLB. Ini enggak pakai perspektif disabilitas. Begitu melihat ada orang dengar yang bisa berbahasa isyarat, ya sudah ajak saja jadi JBI. Padahal itu teman-teman tuli sangat enggak nyambung (komunikasinya),” jelasnya.
Sebagai informasi, FGD ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penanganan kasus KBGD yang dialami oleh penyandang disabilitas, serta informasi terkait pelaksanaan sistem rujukan berbasis pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas korban KBGD. Selain Bantul, diskusi yang sama juga melibatkan penyedia layanan dari daerah lain, yakni Jombang dan Garut.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah advokasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas korban kekerasan yang terlaksana dengan dukungan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Temuan-temuan yang diperoleh di dalam diskusi ini akan digunakan untuk mendukung penysunan kertas kebijakan terkait sistem rujukan inklusif yang akan diadvokasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
“Setelah ada policy brief, harapannya KemenPPPA bisa menyusun kebijakan tersebut, baik kebijakan secara terpisah, ataupun kebijakan yang terpadu dengan kebijakan-kebijakan yang lain,” kata Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)