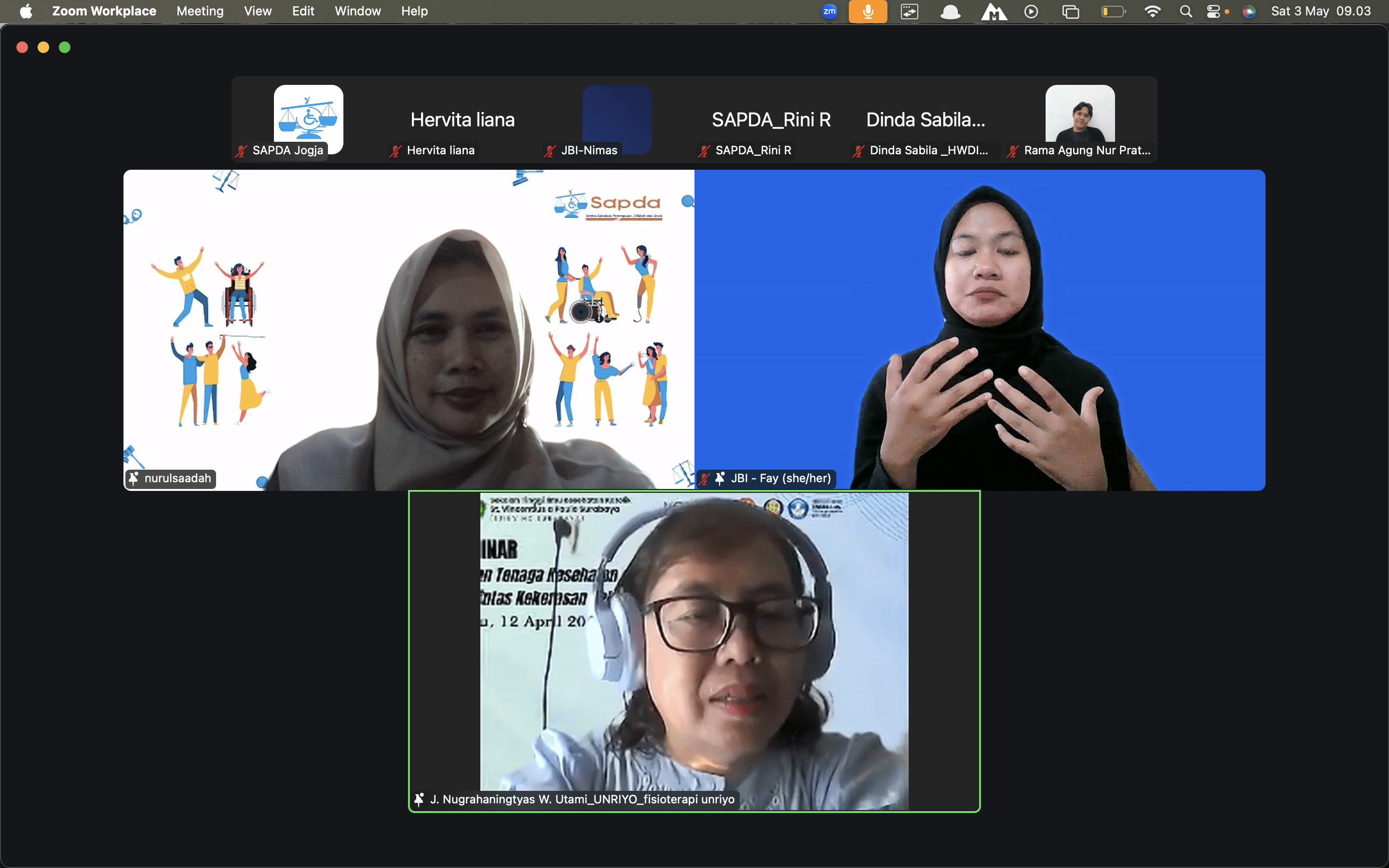Berbagai perwakilan lembaga penyedia layanan asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, membagikan pengalamannya masing-masing saat terlibat di dalam penanganan sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas. Kendati sudah cukup berpihak pada korban dan berhasil membawa pelaku sampai hukuman pidana, namun prosesnya tak dapat dipungkiri penuh dengan tantangan.
Ridi, dari Pusat Kesehatan Masyarakat Malangbong mengatakan, tantangan paling dirasakan ketika berkomunikasi dengan korban yang diketahui memiliki hambatan pendengaran sekaligus intelektual. Hambatan ganda tersebut membuat perlibatan Juru Bahasa Isyarat tidak memudahkan proses menggali informasi dari korban. Persoalan ini kemudian baru teratasi setelah melibatkan keluarga korban sebagai penerjemah.
“Korban tidak menggunakan bukan bahasa isyarat baku, tetapi mungkin bahasa isyarat maternal, atau bahasa ibu. Karena ada kesulitan berkomunikasi, maka (penggalian informasi) lewat ibunya,” katanya ketika menjadi peserta dalam diskusi kelompok terarah Sistem Rujukan Berbasis Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas, yang diselenggarakan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) pada Rabu (22/5) lalu.
Tantangan juga dirasakan pada proses pemulihan kondisi sosial dan ekonomi korban. Hal ini misalnya disampaikan oleh Widi, peserta lainnya dari Dinas Sosial Kabupaten Garut. Ia mengatakan, kendati telah menyediakan fasilitas administrasi kependudukan dan bantuan sosial, pihaknya masih sulit untuk memastikan korban mampu kembali berpartisipasi di masyarakat. Apalagi bantuan yang diberikan hanya bersifat sementara.
“Bagaimanapun keluarga harus memiliki planning ke depannya, bagaimana kebutuhan-kebutuhannya akan dipenuhi. Ketika kami tanya adakah ke depannya ibu berpikir untuk jualan atau bagaimana, saat ini belum ada jawaban dari ibunya. Jadi, masih seperti kebingungan gitu,” ujar Widi yang terlibat di dalam penanganan kasus sebagai pekerja sosial.
Selain itu, proses memberdayakan korban juga memiliki tantangannya tersendiri. Baridah, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, korban memang telah mendapatkan akses pelatihan keterampilan yang akan membantunya hidup secara mandiri. Kendati demikian saat ini belum ada kebijakan spesifik yang memfasilitasi program pemberdayaan ekonomi berperspektif disabilitas.
“Jadi untuk korban-korban kekerasan, terutama perempuan, kami memberikan kegiatan pelatihan tata rias, pelatihan tata boga, dan pelatihan tata busana. Tujuannya agar mereka punya kegiatan usaha produktif, supaya secara ekonomi mereka bisa mandiri. Namun, berhubung banyak keterbatasan, kami belum sampai ke sana (menyediakan pemberdayaan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas),” ujarnya.
Sebagai informasi, FGD ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penanganan kasus KBGD yang dialami oleh penyandang disabilitas, serta informasi terkait pelaksanaan sistem rujukan berbasis pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas korban KBGD. Selain Garut, diskusi yang sama juga melibatkan penyedia layanan dari daerah lain, yakni Jombang dan Yogyakarta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah advokasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas korban kekerasan yang terlaksana dengan dukungan pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Temuan-temuan yang diperoleh di dalam diskusi ini akan digunakan untuk mendukung penysunan kertas kebijakan terkait sistem rujukan inklusif yang akan diadvokasikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
“Setelah ada policy brief, harapannya KemenPPPA bisa menyusun kebijakan tersebut, baik kebijakan secara terpisah, ataupun kebijakan yang terpadu dengan kebijakan-kebijakan yang lain,” kata Direktur SAPDA Nurul Saadah Andriani.




![[DOWNLOAD] BUKU DALAM BINGKAI INKLUSI: PENYANDANG DISABILITAS & HUKUM Sampul buku menunjukkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan sesuai ragam disabilitasnya. Tulisan: Dalam bingkai inklusi Penyandang disabilitas dan hukum (sebuah panduan singkat mengenal sistem hukum di Indonesia untuk penyandang disabilitas)](https://i0.wp.com/sapdajogja.org/wp-content/uploads/2024/11/Dalam-Bingkai-Inklusi-Penyandang-Disabilitas-dan-Hukum-SAPDA.png?resize=150%2C150&ssl=1)